PENGANTAR
KERJA MANUSIA DAN MATAHARI -Sudut-sudut Cerita Masa Silam Bagian I
Penulisan kali ini terbit. Demi untuk yang akan datang. Dalam memetik sekuntum bunga sebuah sudut cerita.Dari belukar pengalaman sekelompok manusia anak bangsa yang terenggutkan hak kebebasan hidupnya selaku warga negara.
Di manakah saat-saat sudut cerita itu terjadi? Tak lain pada selama kurun waktu, ketika sejak meletusnya peristiwa ’65. Suatu peristiwa masa lalu yang betapapun sudah berlangsung kurang lebih setengah abad.Namun, bagi mereka yang selalu bertekad melawan lupa, tak pernah pudar dalam ingatan dan kenangan.
Bagi saya pribadi yang mengalami secara langsung.Baik selaku saksi, maupun sebagai pelaku sejarah yang utuh.Sudut cerita ini, sedaya upaya mungkin jauh terurai dari fiktif.
Seorang kawan, pengasuh tabloid “Urbana” Budi Dayak Kurniawan.Pernah menyarankan kepada saya beberapa tahun yang lalu.Agar supaya saya dapat menuliskan pengalaman yang paling berkesan selama 13 tahun selaku tapol di Kalsel. Lantas saya pikirkan dan renungkan kebelakang, atas apa yang terjadi disana. Ternyata, memang benar rupa-rupanya bukan tidak ada hal-hal yang menarik untuk dituliskan.
Masih segar dan terang benderang dalam ingatan saya. Bahwa penderitaan atau duka derita yang dirasakan oleh para tapol dalam sebuah oase kehidupan kamp tahanan yang tersebar di seluruh tanah air. Tidak sama sebangun, tapi masih agak serupa. Katakanlah, kebanyakan tak jauh berbeda di antara daerah-daerah Nusantara yang ada, satu sama lain.
Kecuali, buat beberapa daerah tertentu. Misalkan Pulau Buru, sebuah daerah tanah gersang dan tandus di kawasan perairan laut Maluku sana. Juga Jawa Timur dan Jawa tengah, karena pengalaman terjadinya aksi-aksi sepihak perkara tanah.Di sini, terjadi sebelumnya pengebonan dan pembantaian massal.Baik secara acak maupun sistimatis.
Minus Jawa Barat, sedikit agak longgar, tanpa terlalu ketat represinya terhadap kehidupan para tapol.Barangkali faktor adab budaya etnis Sunda di tanah Priangan yang riang dan ramah ini.Relatif aman tanpa gejolak yang berarti.Tidak seperti daerah-daerah tetangganya di sebelah timur.
Begitu pula di daerah-daerah Sumatera, rata-rata hampir cukup keras represinya.Terutama Sumatera Utara dan Aceh. Saking kerasnya represi pelanggaran HAM berat terhadap korban peristiwa ’65 di Sumatera Utara ini. Sehingga membuat sutradara film Joshua Oppenheimer dalam karya dokumenternya “The Act of Killing” dan “Senyap” mengambil obyek lokasi di daerah ini.
Sedangkan di Kalsel selaku tempat lokasi penulis ditahan selama 13 tahun. Relatif aman, hampir sama dengan di Jawa Barat. Jika di daerah tetangga dekatnya Kalteng, terjadi eksekusi yang agak cukup massal terhadap para tokoh pengurus Partai dan ormasnya di lokasi KM 27.Maka di sini tak ada pengebonan dan pembantaian massal.Tapi, bukan berarti tidak ada korban disini. Memang ada sekitar 2 hingga 3 orang yang tewas akibat penyiksaan dalam saat interogasi. Dan sekitar 6 orang yang mati diberondong karena lari meninggalkan kamp tahanan.
Nah, kembali ke substansi penulisan ini.Mengenai sebuah sudut (fragmen) cerita “suka-duka” seseorang yang terenggutkan hak azasi kemanusiaannya.Dalam arti bukan semata-mata tentang “duka-derita” dari pengalaman seorang tapol peristiwa ’65 saja, di daerah Kalsel.Seperti yang mungkin terbayangkan oleh imajinasi pembaca.Suatu sisi gelap dari seorang pesakitan yang menderita akibat menjadi pecundang.Mereka teraniaya oleh sistem suatu rezim.Di balik tragedi, masih bisa mereka nikmati juga humor-humor yang lucu selaku komedi hidup.Dalam arti tertawa dibalik tangis.
Memang, di sini saya tak berupaya seperti memetik bunga di taman yang asri dan indah.Tapi menjemput kelopak bunga bagaikan helai-helai bulu rambut yang terserak diatas debu dan abu dari puing-puing yang telah hangus. Membutiri pernik-pernik peristiwa dan rangkaian kejadian-kejadian yang saling berjalinan dengan cita rasa kemanusiaan yang bernuansa psikologis.Ketika gelombang situasi politik bergejolak melanda tanah air kita.Membawa mala petaka, tanpa terbayangkan sebelumnya.
Demikianlah, kata-kata pendahuluan dari pengantar penulisan tentang sudut-sudut cerita tentang pengalaman seorang tapol selama ditahan dalam peristiwa ’65 yang lalu.Ditutup dengan suatu pernyataan.
Bahwa, semua bahan cerita masih terkandung dalam memori di benak saya.Akan saya tuangkan kepada pembaca, melalui perangkat gad-get saya, ketikan demi ketikan.Mungkin berupa. Baik serupa cerpen atau reportase literer secara bersambung (serial)..Maupun jenis bentuk literasi apapun juga, itu nanti.Sayapun tak tahu. Semuanya akan mengalir. Ibarat ilham yang terkunyah-kunyah lewat konsumsi santapan makan malam yang menyegarkan mata dari kantuk. Semoga!
SETANGKAI MAWAR DIBALIK PAGAR KAWAT BERDURI (Bagian Kesembilan)

Setelah selama 3 minggu berada di penjara, kemudian kami dipindahkan kesebuah barak tahanan di Silongan. Masih di lingkungan kota Tanjung (Tabalong). Kami digabungkan
dengan para tahanan yang tadinya ditempatkan di desa Marindi. Di sini tugas kami tetap kerja perbaikan jalan.
Jelas di sini keadaannya jauh berbeda dengan berada dalam penjara. Bahkan dibandingkan dengan di desa Marindi. Di bawah suasana kota yang lebih ramai, terasa sekali perubahannya.
Juga kelonggaran bergerak selaku tapol, hanya sedikit dibatasi. Tapi setiap keluar dari barak untuk keperluan tertentu. Di samping dengan izin juga harus selalu dikawal oleh penjaga.
Kerja para tapol kebanyakan menutupi jalan yang bolong-bolong dengan pecahan batu gunung. Jadi lebih sering pindah-pindah tempat. Terkadang untuk mengontrol mana jalan yang rusak untuk diperbaiki. Maka para tapol dibawa berjalan jauh. Sehingga sekali-sekali punya kesempatan berbaur dengan masyarakat setempat. Tapi tentu saja dengan setahu penjaga.
Ada perkembangan lebih lanjut sikap para penjaga yang berjumlah selusin itu. Mereka dibagi di empat unit barak tahanan. Yang hampir semua menggunakan rumah sewaan penduduk kampung Silongan.
Karena sudah selama berbulan-bulan bergaul dengan para tapol. Mereka semakin melonggarkan penjagaan oleh saling percaya. Lagi pula, selain pencurian kelapa di kamp Sungai Bura dulu. Tidak pernah ada lagi kasus-kasus yang membuat mereka memperketat pengawasan.
Di sini, karena sudah secara rutin saya dimanfaatkan mereka sebagai pelukis potret. Maka seperti halnya di Marindi, saya lebih banyak berada di dalam barak dengan tugas melukis. Sementara yang lainnya kerja luar perbaikan jalan.
Kebanyakan saya disuruh mereka memperbesar foto. Jika tidak dari foto dirinya. Paling sering foto ayah, ibu, isteri dan anak-anak atau keluarganya. Dengan bahan tetap sederhana seperti semula dulu. Lukisan hitam-putih di atas kertas hampir setebal karton. Memakai jelaga hitam asap lampu minyak teplok, dibantu pencil HB.
Betapapun tidak sekeras kerja fisik diluaran. Seperti banyak kawan-kawan di perbaikan jalan di tengah alam terbuka.. Namun, sebenarnya melukis semacam itu di dalam barak, lama-lama sangat membosankan juga. Bahkan, terasa semacam siksa tekanan batin. Hanya karena pekerjaan duduk menghadapi yang itu-itu saja ditekuni. Berada dalam kamar barak yang terasa sumpek.
Memang kerja melukis adalah sesuai dengan bakat dan profesi yang saya miliki. Tentu seharusnya menyenangkan. Tapi mungkin karena status tahanan ini bukan ranah bakat seni untuk bergerak dan berkembang. Bakat seni memerlukan ruang kebebasan.
Semua ini, suasananya sangat kontras dengan kenangan selama kuliah di ASRI dan di Sanggar Bumi Tarung. Sekitar 2 tahun yang lalu. Di kala awal mula petualangan berkarya dengan bebas merambah berbagai aliran senirupa. Dengan menggunakan cat tube merk Defoe, kadang Rembradt atau paling tidak Greco yang paling murah. Dengan senang bermain warna melalui kwas di atas kanvas.
Pikiran darah muda (fresh-blood) dengan bebas bergairah dalam pembelajaran. Melalui petualangan aliran seni yang segar. Dari aliran impresionisme yang saya dapat belajar dengan pelukis Sholihin. Lalu ke kubisme temuan Pi asso yang pernah saya kagumi itu. Lantas juga sempat ke dekoratif. Hingga kemudian akhirnya kembali ke realisme.
Ah, itu dulu. Kenangan manis yang berlalu. Tanpa bisa kembali lagi. Kini apa daya. Sebagai tapol, sang pesakitan dalam pasungan. Pensil HB yang sempat tergeletak beberapa menit. Oleh lamunan kemasa silam. Lantas saya pegang lagi dengan kuat. Sebuah pas-foto kecil ukuran 3 x 4 cm yang tadinya terlepas, saya jemput lagi. Dengan mata nanar menelusuri wajah wanita tua dalam foto, ibu seorang penjaga tapol.
Sambil membangkitkan tekad kembali. Saya lanjutkan lagi menggoreskan pensil di atas kertas. Memindahkan wajah ibu tua lewat skala lebih besar.
“Jangan lecehkan kerja ini. Goresan ini salah satu kiat yang nempertanda untuk membuat kau masih bisa hidup. Mengerti! Saya menghardik diri sendiri. Kau harus terus belajar bersyukur. Kau tahu, apa saja yang telah kau capai selama disini?”
“Para penjaga begitu senang dengan hasil kerjamu. Bahkan, apakah kau tak sadar. Jika para penjaga itu telah membolehkan kau menerima order dari luar ? Bayangkan, tapol bisa terima order?”
“Tidak hanya tetangga di sekitar lingkungan barak ini saja. Juga ternyata bisa datang dari jauh. Yang memberkatimu dengan berbagai pemberian atau imbalan. Kadang uang sekedarnya. Meski harus berbagi dengan penjaga. Dan itu bukan selaku peminta yang mengemis. Tapi karena terdapat nilai prestasimu yang mereka hargai.
“Dan bukankah teman-temanmu lainnya jebagian pula menikmatinya? Semua itu cukup sekedar buat pembeli rokok, gula dan kopi. Dalam berbagi kesempatan meraih secuil kenikmatan bersantap bersama kawan-kawan lainnya.”
“Kau harus sadar dan ingat. Kau adalah tapol. Bukan takrim, tahanan kriminal. Imbalan prestasi yang kau dapat bukan hasil curian selaku maling. Jika mereka penumpang bus melemparkan makanan atau uang sepeser dua peser. Tatkala kamu sedang kerja paksa di perbaikan jalan. Kamu tak perlu malu menjemputnya. Sebab kau terima bukan selaku pengemis. Tapi kau adalah buruh jalan yang telah memeras keringat buat mereka bisa melanjutkan perjalanan.”
Ketika saya sedang menarikan pensil di atas kertas. Sambil asyik dilanda lamunan dialog imajiner. Menyadari keberadaan diri dalam situasi sekarang ini. Dengan merenungkan berbagai problema hidup keseharian selsku tapol selama ini.
Tiba-tiba datang kopral Irfansyah membawa tamunya seorang gadis.
“Ini tamu kita minta dilukis,” sang kopral berujar memberi tahu. Saya sejenak terpana. Oleh suatu kejutan langka. Yang mau tak mau menyentuh daya tanggap darurat kita jatuh terkesima. Bagaikan kisah dongeng klasik yang membayangkan turunnya seorang bidadari kebumi yang gersang.
Kami bersalaman, lalu saya menarik kursi buat si tamu duduk. Selama ini, setiap tamu datang minta dilukis kebanyakan hanya memberikan fotonya. Jarang, tamu lainnya diambil poseren. Karena sulit mengatur waktunya, disamping kurang terbiasa.
Tapi kali ini, saya tidak menanyakan fotonya. Saya pikir, karena sitamu layak selaku model. Sangat bagus diambil poseren. Sitamu mencoba membuka tasnya. Tampak rupanya ia mau mengambil fotonya yang tersimpan.
“Tak usah pakai foto. Dilukis langsung saja”, kata saya.
“Hehehe, malu,ah!”, sitamu alias sigadis merajuk tertawa sambil tersipu.
“Dilukis langsung agar supaya hasilnya lebih bagus. Lebih nyeni! Baik sebagai karya kenangan bersejarah”, saya menimpali dengan nada nembujuk.
Kesan pertama atas kedatangan tamu minta dilukis. Kali ini, memang beda dari biasanya. Meski pada awalnya ia tampak pura-pura menolak diambil poseren. Tapi, kini ia dengan wajah gadis periang yang ceria, bisa duduk anggun sebagai model di depan saya. Kopral Irfansyah yang ternyata punya hubungan keluarga dengan sigadis, meninggalkan ruangan.
Kertas lukis saya tempelkan di atas papan lapik yang saya sandarkan ditiang sketsel manual. Jadi saya melukis dalam keadaan berdiri. Beda dengan cara saya melukis foto ibu tua yang belum selesai itu. Duduk menekuni gambar di atas meja kecil.

Dari sambil melukis, kami ngomong ngobrol. Tahulah saya, bahwa sang model bekerja selaku pegawai di BRI cabang Tanjung. Ia anak tunggal semata wayang dari orang tua sebagai pedagang kelontong. Tamat SMA, tanpa melanjutkan kuliah.
Tampak pada gerak gerik, sikap dan bicaranya. Sekali lagi, sigadis seorang periang ceria yang lincah. Usianya sekitar 17-an kira-kira dalam tebakan saya.
Seperti yang telah tergambar di latar kertas yang terpajang. Ia memang bisa dikatakan tergolong berwajah cukup cantik. Ini menurut penilaian sa
ya. Entah bagi orang lain. Tentu bisa relatif bagi setiap selera penilaian orang masing-masing. Apalagi tentang estetika raut paras seseorang. Terkadang sangat subyektif.
Dalam durasi waktu sekitar satu setengah jam. Lukisan potret drawing hitam putih ini sudah mendekati selesai. Tinggal finishingnya saja lagi. Saya merasa ada beberapa detail aksentuasi yang diperlukan perampungan lebih dalam.
“Silahkan lihat dulu! Tapi masih belum selesai. Situ, ah maaf tolong sebutkan namanya”, saya meminta. Ia beranjak dari duduknya sambil, mengenalkan nama: “Tiar, panggil saja nama saya Tiar”.
“Tiar kan izin kantor katanya cuma 1 jam saja. Kalau bisa besok disambung lagi”, saya berkata mengingatkan.
“Wahh, hahaha…cantik, juga yaa ?”, ia tertawa melihat lukisan wajahnya, sambil berkata mengandung tanya. Saya mengangguk, sambil tersenyum berkata, sekedar jawaban basa basi :” Ahh…tidak juga. Masih lebih cantik orangnya yang nyata”. Ia kembali tersipu dengan jengah.
Perkenalan pertama di antara “pelukis tapol” dengan “gadis model” seorang pegawai BRI, boleh dikatakan cukup mulus. Tampaknya semacam suatu peretasan garis batas berkawat duri. Ini hanya bisa terjadi karena kebijakan perorangan penjaga. Tapi juga ada segelintir atau lebih di antara masyarakat yang tak menghiraukan phobia yang telah bersarang dalam tubuhnya secara massif oleh kekuasaan Orba. Ditambah keberanian perorangannya yang nekad oleh tekad bulatnya. Bagi kebanyakan orang awam bisa dianggap tak waras atau berotak miring.
Tiar, nama gadis yang berani itu. Seperti juga mereka lainnya yang meretas kawat berduri. Hanya sekedar memesan lukisan foto kepada seorang pelukis tapol. Tidak peduli lagi dengan keamanan sistem larangan politik dan ideologis yang ditegakkan penguasa baru.
Pada peristiwa beberapa bulan yang lalu, para tapol menjadi tontonan yang menarik. Di mana, sebagian terbanyak menyaksikan dengan pandangan mata yang sinis. Mereka, para tapol yang dipekerjakan paksa membersihkan sampah di lapangan itu. Dianggap tidak lebih merupakan monster jahat pembunuh kejam perwira militer “pahlawan revolusi”
Untung saja mereka diberi kesempatan selamat hidup. Dibermanfaatkan sebagai manusia. Coba lihat di tempat-tempat yang lain. Misalnya di Jawa dan Bali mereka dibantai tinggal bagai tikus mati terlempar di got-got, pinggir jalan dan sungai-sungai.
Kini, dalam suatu proses dialektika yang tak lazilm alias langka. Si gadis model bernama Tiar itu, telah menjelma bagaikan sepucuk mawar yang tumbuh bersemi menjuntaikan tangkainya di kawat berduri suatu pagar pembatas. Dalam arti kiasan metafora.
Karena sejak ia dilukis pertama kali. Ia telah berulang kali berkunjung kebarak tahanan. Yang betapapun sebenarnya tak berpagar kawat berduri secara kasat mata. Tapi nyatanya ia dengan mulus menyelinap kedalam barak tahanan melalui para penjaga bersenjata laras panjang. Benih cinta yang terlarang mulai merambat melayapi rentang kawat berduri di sekitar barak para tapol yang sebenarnya terisolasi.
Kami hanya sekedar bersilaturahmi kemanusiaan. Bukan dalam urusan yang ada kaitannya dengan perkara politik atau ideologi. Tapi, kenapa bisa jadi?
Ini tentu semacam pengecualian. Atau suatu kelainan situasi yang bernuansa paranoid. Saya tahu diri, berupaya memberi pengertian kepada Tiar siapa saya. Tentu saja siapa dia. Dalam konteks situasi kekuasaan politik. Bisa berbahaya dan merugikan bagi yang bersangkutan.
Kopral Irfan saudara sepupu Tiar, sudah beberapa kali mengingatkan. Tapi, kopral Irfan pula yang memberi tahu bahwa Tiar, memang anak bandel. Maklum anak tunggal semata wayang. Sehingga akhirnya ia dijadikan Tiar, tak saja selaku sepupu atau keluarga yang baik. Tapi juga sebagai mitra Tiar yang terpaksa membantu kami meneruskan hubungan yang terlarang ini. Sungguh dilematis atau seperti menghadapi buah simalakama bagi kopral Irfan.
Namun, bagi saya lebih-lebih lagi repotnya. Memang saya tak munafik! Kedekatan kami secara pribadi bukan berarti tanpa saling menyukai. Bahkan, apakah itu sudah bisa dibilang bernuansa semacam rasa cinta. Hati nurani saya pribadi, lama kelamaan, bukan saja tak menolak, tapi juga mengamini.
Jelas dan pasti ini suatu pergulatan yang cukup menegangkan dalam diri saya belakangan ini. Sebab, saya harus secara mutlak, sadar untuk tetap tahu diri. Bahwa saya adalah tapol yang tak berdaya. Dalam arti tak bisa diharapkan kapan bebas. Seandaikata bikin janji kepada seseorang bagi kepentingan bagaimana saja.
Dalam keadaan galau begini, sayapun teringat kepada Tanrangsuli yang berada di pegunungan Meratus sana. Gadis dayak yang eksotis itu telah bisa kami kagumi, tapi dari sisi lain. Suatu perasaan welas asih atau rasa kasihan kemanusiaan. Buat diidolakan sebagai simbol kemurnian jiwa manusia dalam kehidupannya bersama lingkungan alam.
Tapi, terhadap Tiar. Mungkin sebagai salah satunya. Bagaikan bunga mawar dalam keadaan segar di kota Tanjung ini. Sangat terasa beda. Mau tak mau harus diakui terdapat suatu getaran organ biologis yang tak terhindarkan.
Terus-terang saya tidak mau munafik. Bahwa daku sebagai lelaki yang punya hati kejantanan tak menafikan atas adanya sentuhan libido Freud terhadap terhadap lawan jenis kelamin.
Dulu, tatkala di SMA hingga kuliah ASRI di Yogya, saya termasuk pemuda remaja yang tak peduli pacar-pacaran. Karena begitu asyik tenggelam oleh ekstasi berkarya nyeniman bohemian. Kemudian setelah ditambah sibuk di organisasi Lekra, emej tentang perempuan semakin kabur. Dalam arti banyak terlupakan.
Tetapi sekarang? Di usia hampir mencapai 25-an ini. Bisa jadi sudah tiba saatnya diumbar lapar kemaruk. Apalagi terasa ada sentuhan pesona khusus tertentu. Bahwa dimulai dengan pandang pertama, ketika saya berhadapan dengan Tiar sebagai model poseran. Di sinilah mungkin terjadi berawal dari seletik titik embun yang jatuh disaat kemarau panjang. Lalu berubah menjadi gerimis menyirami bumi yang gersang kerontang. Dan sangat dimungkinkan akan turun hujan lebat.
Namun, celakanya situasi kini ini amat tidak kondusif. Kenapa saya harus jatuh cinta di saat-saat begini? Seorang tapol dalam pasungan. Jikapun saya benar-benar jatuh cinta yang serius. Tetap saja orang bilang. Seperti burung pungguk rindukan bulan.
Peristiwanya kini, hujan kadung turun lebat. Dan jarang hujan lebat tanpa guntur dan petir. Bahkan berbadai sekalian. Nyatanya kini burung pungguk kemasukan pasangannya di dalam sangkar. Tak boleh jadi. Saya semakin resah bukan saja karena mabok kepayang. Tapi gosip selentingan menerpa kami dari sana sini. Baik dikalangan penjaga maupun di lingkungan kawan-kawan para tapol.
Saya semakin banyak cemas dan gugup. Justeru frekwensi kunjungan Tiar menemui saya kian meningkat di dalam barak. Suatu hari Tiar mendesak dan menekan saya dengan pertanyaan yang cukup berat untuk saya jawab.
“Ada soal apa kak Tamrin! Kenapa kelihatan gelisah?” Tanya Tiar kepada saya sambil menatap mata saya.
“Ahh, tidak apa-apa,” sahut saya. Ia terus tetap tampak merajuk, karena tak puas saya dianggapnya tidak terus terang.
“Apa lantaran soal kita? Kalau begitu saya tak usah datang lagi kemari, menemui kak Tamrin,” dengan meruncing kata-kata tajam Tiar menusuk pengakuan saya.
“Jangan begitu, dik Tiar. Benar, tidak apa-apa. Biasa dan tenang sajalah,” saya berkata agak terbata-bata karena terganggu oleh rasa cemas dan gugup. Tapi segera berupaya kembali bersikap tampil percaya diri.
Baru kali ini kami terlibat dalam konflik yang rawan. Bayangkan, hanya lewat sekelebat mata panah emosi terlepas dari busurnya. Bisa jadi sebagai biang pertanda tersulutnya letikan api yang dapat membakar padang ilalang.
Begitulah proses dialektik alur suatu perjalanan petualangan romantisme cinta yang terniscaya dalam kelaziman. Seperti dalam perkiraan. Ibarat dari setitik embun menjelma gerimis, lantas terpacu oleh hembusan angin untuk kemudian menuai badai demi badai.
Saya terpaksa berdusta dengan Tiar tentang apa yang tengah terjadi sebenarnya. Bukan karena khawatir kehilangan momentum sambung rasa cinta yang berharga di antara kami. Tapi saya tidak tega mengungkap perkara sebenarnya yang saya anggap daya nalar Tiar tak sanggup mencernanya secara dewasa.
Saya merasa itulah kekurangan seorang yang suka berada dalam keseimbangan ranah abu-abu (grey-area). Sulit menetapkan pilihan diantara hitam dan putih secara tegas. Dan sementara itu beban yang menekan jiwa saya begitu berat, adalah selentingan gosip diantara kawan-kawan saya sendiri. Mereka mengkhawatirkan jika ini merupakan sebuah skandal pencemaran yang dampak akibatnya bisa merugikan nasib para tapol secara keseluruhan.
Bagi para penjaga, mungkin karena peran kopral Irfan yang telah mencoba menetralisir teman-temannya. Tampak seakan-akan cuek saja. Tapi naluri politis yang bekenyamuk dalam benak saya. Bukan saja soalnya akan menuai efek berbahaya bagi saya sendiri, tapi juga bagi Tiar.
Di saat-saat tenggelam dalam gelimang keresahan itu. Saya hanya berharap atas bio ritme keramahan waktu untuk mendapatkan giliran yang adil. Sementara Tiar sudah beberapa hari tak muncul. Sesuai dengan janjinya yang dinyatakannya secara emosional. Dicelah peristiwa konflik pertama kali terjadi di antara kami yang cukup rawan.
Sampai tiba saatnya, suatu kebetulan seperti yang diharapkan. Sesuai dengan gagasan yang pernah saya pertimbangkan secara realistis. Sore itu kopral Irfan datang memberi tahu. Bahwa besok saya diberangkatkan ke Banjarmasin. Atas panggilan tim pemeriksa daerah Kalsel.
Saya tidak terlalu kaget. Karena sebelumnya pernah saya perkirakan. Bahwa saya selaku dianggap petugas atau utusan partai dari Banjarmasin. Sudah dapat dipastikan suatu saat saya akan dikembalikan kesana. Hanya berita ini akan menimbulkan dampak lanjut kepada hubungan kami. Di antara saya dan Tiar. Sebuah risiko dan konsekwensi yang tak terhindarkan.
Pada malam harinya, sesudah sholat Isa, dengan menumpang di boncengan sepeda yang dikayuh oleh kopral Irfan. Kami pergi menuju kerumah Tiar. Sudah dapat diduga, sikopral sudah terlebih dahulu memberi tahu Tiar sebelumnya tentang keberangkatan saya besok. Atas prakarsa Tiar, malam perpisahan kami diadakan dirumahnya.
Rupanya di serambi rumahnya, Tiar telah menunggu kami. Saya sipersilahkan duduk di ruangan tamu. Sedangkan kopral Irfan terus masuk kedalam ruangan keluarga. Barangkali untuk menjumpai orang tua Tiar, karena mereka berkeluarga.
Sejak sekali peristiwa konflik kami hampir sepekan yang lalu itu. Terasa begitu lama kami tak bertemu.Tentu secelah rasa rindu menyelinap di hati kami masing-masing.
Selama beberapa menit, kami dalam keadaan berdiam diri, seperti terbungkam. Sayapun larut terpaku tanpa bicara sepatah kata. Seakan peristiwa konflik yang lalu itu masih bersisa membekas. Tiar tampak agak gamang dan rikuh. Hingga ia bangkit berdiri pergi masuk ke ruangan dalam.
Ditinggal sendiri, saya sempat memandang potret Tiar yang saya lukis, terpajang di dinding. Tampak dikemas dengan pigura berkaca yang cukup rapi dan bagus. Lantas sejurus kemudian, Tiar muncul dengan dua buah cangkir minuman dan seples kue kering di atas baki.
Setelah ia duduk, sambil menyilahkan saya minum seadanya.
“Saya diberi tahu Irfan, besok kak Tamrin ke Banjarmasin. Apa sendirian tanpa yang lainnya?”, Tiar membuka dialog.
“Syukur alhamdulillah,saya diberi tahu sebelumnya. Biasanya jarang begitu. Selalu dadakan. Tak mungkin kita bisa bertemu seperti begini, sebelumnya. Iya, saya dijemput sendirian, tanpa yang lain,” jawab saya dengan rasa senang yang merambat.
“Alhamdulillah, berkah buat kita, bukan?” Ia menimpali, sambil tersenyum. Sayapun mengangguk, sambil ikut bersenyum.
Gesekan sambung rasa yang tersisa dari peristiwa konflik yang lalu itu, melembut bagai kapas. Seolah itu tak pernah terjadi. Kini yang muncul bergetar adalah rasa sayang kebersamaan yang syahdu. Mungkin ini sudah semestinya hadir. Justeru pada saat-saat singkat di malam perpisahan kami ini.
“Kak Tamrin, kalau sudah di Banjarmasin apa bisa menulis surat buat saya?” Tiar memecah kesunyian, dengan kalimat tanya yang sendu yang nelangsa. Dengan pandang sepasang matanya yang menggali dan menelusup kedasar relung hati saya.
“Pasti akan saya upayakan. Jika tak mungkin lewat pos. Saya akan kirim surat melalui keluarga saya.” Saya menjawabnya dengan upaya tenaga yang ada untuk meyakinkannya.
Kemudian ia mengalihkan pandangannya. Seolah menatap jauh menyusuri lewat punggung saya hingga menembus dinding ruang tamunya. Tampak sepasang matanya berkaca-kaca. Lalu tergenang oleh gelimang air mata dan menetes perlahan.
Saya menyeberangkan badan saya lewat meja tamu. Bergeser mendekati dirinya. Dengan menyentuh jari tangannya hingga beberapa detik, kami saling bergenggaman tangan. Seraya gestur tubuhnya bergerak seperti akan rebah kedinding dada dan bahu saya.
Namun momen yang amat berkesan bagi kami ini, terhenti dan terbatalkan oleh suara ajakan ibunya bersantap makan malam. Dan Tiar segera menyeka wajahnya yang sebak oleh basah air matanya dengan jari telapak tangannya.
Di ruangan makan, kedua orang tua Tiar saya salami dengan sembah sujud tanda perkenalan pertama kami. Kesempatan itu diawal kedatangan saya sempat tertunda. Demi sepenuhnya, di malam pertemuan dan perpisahan kami berdua yang singkat itu. Selama berada di rumah mereka, dapat dimanfaatkan dengan agak bebas.
Menghadap meja makan malam, kami berĺima, termasuk kopral Irfan. Menikmati santapan masakan Banjar yang bagi saya cukup langka selama ini. Kehilangan kesempatan makan bersama dengan keluarga dan para sahabat semacam ini. Terasa begitu lama, seakan telah berbilang tahun.
Di pagi bergerimis, dengan cuma dikawal seorang perwira bawahan CPM. Telah meluncur kendaraan jip militer yang kami tumpangi menuju Banjarmasin. Melalui kaca mobil arah kedepan, terbayang memori yang berlalu di belakang. Kawan-kawan setapol, para penjaga barak, Tanrangsuli dan Tiar. Mereka semua tersimpan dalam album kenangan yang tak terlupakan.
Kesan dari kedua mereka, Tanrangsuli dan Tiar punya kesamaan dan perbedaannya. Keduanya melekat dalam ingatan, selaku icon. Bagaikan dewi inspirasi yang memberikan gairah atas hidup yang indah ini.
Jika Tanrangsuli gadis Dayak yang eksotis itu. Begitu sederhana, polos, lugu dan lugas dengan kemurniannya yang secara simbolis selaku mahluk alam tak tersentuh.
Maka Tiar jauh berbeda. Sebenarnya dia sebagai anak tunggal semata wayang yang manja. Tetapi juga ia adalah gadis bengal pemberani yang nekad. Tanpa penyuluh lampu pikiran, menerabas pagar pembatas kawat berduri.
Iapun punya air mata kesedihan. Jika ia sebagai anak manja, terbiasa memprotes ibunya dengan tangisnya, bila kehendaknya tak terkabulkan. Maka kini ia akan tahu dan sadar. Bahwa airmatanya tak cukup berarti, untuk tidak dikatakan sia-sia. Tatkala berhadapan dengan benturan kekuasaan rezim otoriter yang kejam dan tanpa ampun… .
***
Banjarmasin, Januari 2017
KOTA DI ATAS AIR SERIBU SUNGAI (Bagian Kesepuluh)

Di sekitar kawasan Binuang, jip militer yang kami tumpangi. Memacu laju kecepatannya di jalan yang lurus. Melalui kaca mobil, tampak dikejauhan pegunungan Meratus memunggungi langit biru. Betapa indahnya pemandangan alam mempersaksikan dirinya. Sebagai salah satu bagian gugusan bagi pecinta tanah air, kita tanamkan di sini.
Wilayah ini disebut daerah Kalsel. Di mana bermukim kebanyakan orang Banjar. Penduduk salah satu etnis dari keberagaman Nusantara yang kaya raya. Menghuni ribuan pulau yang tersebar membentang dari Sabang ke Marauke. Bagaikan untaian mutiara atau sabuk zambrut. Mengalungi leher salah satu kawasan dunia yang menjembatani 2 buah benua. Asia dan Australia.
Terkadang tampak iringan beberapa ekor kuda berjalan dipinggir jalan. Membawa jagung dalam karung di kiri kanan punggungnya. Para penunggangnya adalah orang-orang petani transmigran dari suku Madura. Pendatang asal dari daerah etnis lain yang sudah lama bermukim di sini.
Daerah ini bagian dari Indonesia yang tercinta. Salah satu daerah otonomi dalam naungan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan ke Bhinnekaan Tunggal Ika. Mungkin demikianlah sebaiknya keberadaan negeri kita ini. Sejak para founding farther, terutama oleh sang proklamator Bung Karno, tampil mendeklarasikan.
Namun, lembaran waktu yang terhampar. Berada dibawah sistem kekuasaan yang mulai berubah. Dari semua ini. Kini, saya selaku tapol. Pecundang dari suatu korban perebutan kekuasaan. Berada dalam pasungan aparat rezim penguasa baru. Di dalam mobil jip militer yang sedang berpacu menuju Banjarmasin. Kota di atas air seribu sungai.
Setibanya di kota Banjarmasin, saya di tempatkan pada salah satu ruangan tahanan markas CPM Daerah Kalsel. Ternyata, saya bisa berjumpa kembali dengan kawan-kawan rekan sekerja ormas Lekra yang di ditahan di Banjarmasin. Mereka kebanyakan rata-rata sudah selesai dalam pemeriksaan.
Pada pertengahan tahun 1964, saya mulai bermukim
dan bekerja di kota ini. Sejak sekitar 5 tahun (1959-1964) saya tinggalkan. Selama itu pula saya berada di Yogya. Kuliah di ASRI, sambil lebih banyak berbohemian dan berorganisasi di Sanggar Bumi Tarung.
Sebelumnya, sejak tahun 1953, hampir sekitar 6 tahun sebagian masa remaja saya berada di kota ini. Sekolah SMP dan SMA, saya lalui dan sudahi di sini. Jadi, bagaimana sentuhan keberadaan saya mengenyam suasana nafas dan detak jantung kota ini. Mereguk air sungai dari padanya, tawar, asin dan manisnya sudah saya kecap dan rasakan secara intens. Hingga kepada perangai sedalamnya, telah saya duga dan kenal lebih akrab.
Dari pasang surutnya air sungai. Dengan taburan kiambang di atas permukaannya yang larut bolak balik. Perahu-perahu yang meluncur dikayuh para pedagang yang menawarkan jualannya. Buat pembelinya di rumah-rumah lanting terapung. Atau bisa juga dari tangga dapur rumahnya yang menjorok di tepi sungai.
Suatu fakta realitas yang giris dan rawan. Ketergantungan warga penduduk masyarakat terbanyak di sini terhadap sungainya. Air sungai adalah berkah utama bagi hidup mereka. Buat minum, mandi, cuci dan membasuh segala apa saja yang diperlukan.
Lewat batang terapung yang dibuatkan “jamban” nya. Mereka mencuci pakaian, bermandi dan membuang tinja beserta kotoran lainnya di sana.Tapi, lama kelamaan demi penertiban kesehatan dan pemandangan. Secara bertahap, kebiasaan tradisi membuat jamban di tepi sungai telah ditiadakan. Baik dari sini, maupun hingga jauh ke kawasan Hulu Sungai Utara.
Begitulah, hidup membudaya di sini bagi saya pribadi. Terasa menyerap dalam batas tertentu. Seakan-akan perangai manusia penghuninya, telah terbentuk oleh pengaruh alam lingkungan. Dengan bukti-bukti yang bisa diuraikan. Cuma dengan alasan bagaimanapun, saya hanya terpikir sebatas asumsi semata. Dan mungkin nanti akan lebih jauh bisa kita bahas dalam kaitan masalah lainnya.
Sementara kesan yang terpendam dalam gagasan saya selama ini. Mengenai kota Banjarmasin yang baru saja saya jumpai lagi. Setelah belum sampai setahun saya kembali ke sini. Sejak saya tinggalkan selama 5 tahun bermukim di Yogya. Lantas meletus peristiwa ’65, saya tinggalkan lagi kota ini. Karena selama beberapa bulan saya selaku tapol berada di kamp atau barak tahanan di Hulu Sungai Utara.
Tak seberapa lama kemudian, saya tersentak oleh panggilan dari Pomdam. Perkiraan saya, itulah rupanya jadwal sesuai dengan rencana. Kembali menghadap tim pemeriksa. Ada terlecut rasa cemas dan gugup. Layaknya sebagai gangguan traumatis dalam benak saya. Ingatan yang luka oleh tragedi yang menyakitkan, mungkin berulang lagi.
Seorang sersan CPM membawa saya dari kamar tahanan. Menuju kantor markas Pomdam yang berjarak dekat. Hanya sekitar berpuluh meter. Karena kamar tahanan tapol satu komplek dengan kantor Pomdam.
Ternyata saya dibawa masuk keruang intel Pomdam. Di sana, duduk menghadap meja, Letnan Anang Prawira. Beliau saya kenal sebelumnya. Sejak sebelum peristiwa ’65 meletus. Sering betemu dalam pergaulan pada setiap pertemuan di Front Nasional.

“Bagaimana kabarnya saudara Tamrin, sehat?”
Sang Letnan menyapa dengan ramah, sambil menyalami saya. Suara perkataannya yang bernada logat Sunda yang kental, seperti yang saya kenal. Tetap tak berubah.
“Alhamdulillah, masih sehat wal’afiat, pak”. Saya nenyahut dengan sikap hormat. Sambil membiarkan salam jari tangan saya dalam genggaman telapak tangannya yang kekar.
Benar-benar di luar dugaan sebelumnya. Ternyata saya bukan menghadapi pemeriksaan dari tim interogator. Tapi dipanggil oleh Letnan Anang Prawira yang berbadan bongsor, tapi seorang peramah yang simpatik.
Beliau memberi tahu saya. Bahwa saya nanti akan di bon kerja luarkan di rumah kediaman Panglima Kodam AD dan AL. Bahkan sesudahnya nanti juga oleh Komandan Markas CPM. Dengan tugas melukis potret para tokoh penjabat top daerah tersebut. Besok kata beliau, dimulai di rumah Panglima Kodam AL Laksamana Rudjito.
Kenapa dan dari mana, kesempatan ini muncul? Yang bisa saya duga kemungkinan besar. Karena dulu, sebelum peristiwa ’65, saya pernah melukis potret pak Letnan Anang. Beliau kenal dan bersahabat baik dengan saya. Berhubung selaku Komandan Intel CPM yang duduk juga di Tim Pemeriksa para tapol. Sehingga ia tahu keberadaan saya.
Memang suatu berkah keberuntungan. Anugerah bakat melukis yang saya dapat cukup berarti dan bermanfaat. Justeru pada saat dan momen ketika nasib malang menimpa diri saya. Seperti selaku tapol yang dipekerjakan bagi kepentingan penguasa sekarang ini.
Sebenarnya di sini, ada 2 orang pelukis lagi. Tapol kawan saya yang berasal dari Lekra yang juga jebolan dari ASRI. Pertama Sudiasih, pelukis asal etnis dari Jawa. Dulu ia juga pernah bergabung di Sanggar Bambu. Angkatan ASRI yang jauh lebih terdahulu dari saya. Kedua, Nyoman Sukerta dari Bali. Angkatan ASRI satu tingkat di bawah saya. Ia saya bawa ke Kalsel untuk memperkuat Lekra. Tapi, saya dengar informasi dari kawan tapol di sini. Mereka berdua berada di kamp tahanan di Liang Anggang.
Begitulah, selama berbulan-bulan saya kerja luar. Jarak di antara kantor Pomdam kerumah Panglima AL cukup dekat, hanya sekitar setengah pal. Mula-mula dikawal, tapi kemudian saya dipercaya berangkat dan pulang sendiri, tanpa pengawal.
Saya melukis di sana dengan peralatan yang tersedia. Merek “Talens” dan “Rembrandt” cat tube mahalan yang disediakan. Lengkap dengan cat minyak dan kwasnya. Termasuk segulungan kain kanvas. Span-ramnya dibantu oleh tukang kayu yang didatangkan. Membuat saya merasa senang bekerja dengan penuh semangat. Melukis panglima AL, ia dengan isterinya, lewat foto. Sesuai permintaan atas foto pilihannya, tanpa poseren.
Sekitar 2 bulan saya bekerja melukis di rumah pak Rudjito, Panglima AL. Di samping melukis potret, juga beberapa lukisan pemandangan (landscape). Suatu kesempatan yang cukup menyegarkan bagi saya. Selaku seorang tapol yang punya bakat dan profesi melukis. Ketimbang di saat-saat sebelumnya. Setiap hari saya pulang ke ruang tahanan dengan diberkati makanan. Kadang uang insentif sekedarnya, cukup buat pembeli rokok, gula kopi dan jajanan lainnya. Untuk keperluan bersantap minum dan makan bersama kawan-kawan setahanan.
Sesuai dengan di janjikan dan direncanakan pak Anang. Lantas saya digilirkan bekerja melukis untuk Panglima Kodam Kalsel, Letjen Sobirin Mochtar. Bekas komandan Batalyon “Sikatan” yang terkenal itu. Menggantikan Letjen Amir Machmud yang dipindahkan ke Jakarta. Jenderal yang temperamental ini, sebelumnya sebagai Panglima Kodam Kalteng. Pada saat ia menjabat Panglima di sini, terjadi pengeksekusian korban para pimpinan PKI dari tingkat daerah Kalteng hingga ranting beserta ormasnya, di awal peristiwa ’65.
Berbeda dengan di daerah Kalsel. Di sini tatkala dibawah kepanglimaan Amir Machmud agak lebih aman. Pengamanan dan ketertiban daerah, pada awal peristiwa ’65 dalam keadaan relatif kondusif. Tanpa ada “genosida” seperti apa yang konon terjadi di sekitar km 27 jalan raya Palangka Raya. Apalagi jika dibandingkan dengan di Jawa ataupun Bali. Padahal saat itu Kalsel termasuk wilayah “3 selatan” (Kalsel, Sulsel dan Sumsel) yang kuat kekuatan anti PKInya.
Saya untuk bekerja melukis, tidak langsung di rumah tinggal Panglima Sobirin Mochtar. Tapi di tempatkan pada “Guest-House” Panglima Kodam di Javahud. Sebuah wisma tempat peristirahatan yang tenang di sekitar pinggiran pantai delta muara sungai Barito yang luas.
Sekedar mencoba, saya usulkan kepada pak Anang. Bagaimana kedua kawan saya Sudiasih dan Nyoman Sukerta yang berada di kamp tahanan Liang Anggang. Bisa kumpul dengan saya di Javahud. Karena sama-sama pelukis. Sehingga kami bisa akan lebih produktif berkarya buat kepentingan Panglima.
Ternyata usul saya diterima. Maka bertiga kami bekerja melukis di Guest-House. Sedangkan tempat tinggal kami kumpul dengan para tapol lainnya. Yang kebetulan mereka sedang dimanfaatkan kerja di pabrik penggergajian gelondongan kayu besar di Javahud.
Kami bertiga tinggal satu rumah dengan keluarga pak Ngalimun. Seorang montir ahli mesin yang juga berstatus tapol. Tapi dibolehkan membawa keluarganya berkumpul oleh penguasa. Jadi, dalam satu rumah cukup besar, tinggal pak Ngalimun bersama isteri, dengan keempat anaknya, Iyul, Onie, Endang dan Djoko. Sedangkan kami, Sudiasih, Nyoman dan saya tinggal, tidur, dan makan bersama keluaga pak Ngalimun. Di bawah payung atap rumah yang sama.

Pada suatu senja, menjelang matahari terbenam. Setelah kami selesai melukis. Kami duduk-duduk beristirahat santai, sambil memandang horizon permukaan sungai Barito yang jauh. Bola matahari yang merah jingga memantulkan cahayanya di atas air yang beriak dan bergoyang.
“Kita tak tahu sampai berapa lama bisa berkumpul seperti ini di sini “, kata Sudiasih melantunkan bahasa hatinya dihadapan kami. Disaat-saat matahari senja kian bergulir menapak cakrawala.
“Bagaimanapun kita tak punya hak untuk berkehendak. Nasib kita sangat tergantung kepada maunya penguasa,” sahut Nyoman menyampaikan pendapatnya.
“Tapi sebaiknya, justeru mungkin kesempatan kita berkumpul ini sangat terbatas. Lebih baik kita manfaatkan secara maksimal. Situasi sekarang cukup baik bagi kita. Karena agak sedikit bebas kita bisa berkerja sesuai dengan bidang kita. Dalam status tahanan, tapi ini suatu kesempatan kita bisa berkarya seperti orang bebas,” saya menimpali untuk meraih segi positifnya yang ada.
Secara prinsip, kami harus jeli melihat peluang yang terdapat didalam situasi kritis sekalipun. Betapapun telah terbiasa oleh tantangan hidup yang keras. Seperti pengalaman getir yang telah menjadi keniscayaan naluri kami sebagai tapol selama ini.
Tetapi justeru ketika kami bertiga diberi kesempatan berkumpul dalam menghadapi tugas pekerjaan yang seprofesi ini. Selaku tapol yang dipelakukan penguasa. Tentu kami tidak boleh puas diri untuk terlalu senang. Dengan terciptanya kesenjangan di antara kami bertiga dengan kawan-kawan tapol lainnya. Dalam hal beban tugas yang diberikan penguasa.
Jika Nyoman Sukerta diberikan tugas membuat karya pahatan ukiran kayu. Sudiasih membuat lukisan pemandangan (landscape) dan taferil situasi kesibukan “Pasar” di atas kanvas. Maka dalam pembagian tugas atas dasar kesepakatan kami bertiga ini. Saya secara spesial menangani lukisan-lukisan potret.
Di sinilah potensi yang kami miliki. Di samping mereka sebagai penguasa Orde Baru yang belum stabil dan mapan ekonominya. Mereka terdesak memanfaatkan tapol secara produktif. Dari pada harus menyediakan biaya terus menerus buat makan para tapol. Secara nasional ratusan ribu jumlahnya. Dari mana budgetnya dicari?
Itulah masalah yang krusial bagi penguasa. Jika harus dikurangi jumlah tapol, melalui genosida seperti yang terlanjur terjadi di Jawa dan Bali. Kendalanya itu merupakan pelanggaran HAM yang menjadi sorotan dunia.
Maka kini sangat terasa bagi kami. Manfaat tapol bagi penguasa untuk “dikaryakan” sebagai kata ganti “di kerja paksakan”. Dunia terniscaya untuk mengannggapnya tak manusiawi jika “dilenyapkan” selaku nyawa umat manusia. Sehingga kami bertigapun merasa wajar untuk memaklumi. Jika sekarang, tenaga dan bakat seni kami. Dimanfaatkan alias dieksploitasi bagi kepentingan biznis atau usaha keuntungan apapun bagi penguasa Orba.
Untuk itu, bagaimanapun di balik ketidak berdayaan kami selaku tapol yang ditentukan. Tinggal mengharap dari daya upaya yang ada. Mungkin terdapat secercah rezki yang menetes dari celah lubang genggaman tangan mereka, dalam mengeduk keuntungan. Dari hasil memeras jerih payah dari keringat pengerahan tenaga dan bakat seni kami, buat mereka.

Matahari senja dengan cahaya pijarnya yang kemilau, di balik nuansa silhuetnya yang berwarna jingga campur merah maron. Semakin merendah mendekati saat-saatnya ia menenggelamkan diri kedalam horizon permukaan sungai Barito yang luas terbentang.
Kami bertiga bersiap untuk memulangkan diri. Meninggalkan wisma guest-house milik seorang jenderal di Javahud yang difungsikan sebagai bengkel kerja 3 orang pelukis tapol. Menuju hunian kumpulan para tapol yang dipekerjakan sebagai buruh pabrik penggergajian kayu.
Mereka bukan orang-orang malang tanpa masa depan. Namun mereka masih bisa bekerja. Bukan hanya karena dipaksa. Tapi, demi membangun harapan. Dari usia dan mimpi mereka yang tersisa.
*** Banjarmasin, Januari 2017
“JAVAHUD” (Bagian Kesebelas)
Tak terasa, waktu berlalu telah berbilang tahun. Bayangkan, tapol bisa lupa dengan waktu. Dan merasa kerasan ditahan. Ironis, bukan? Begitulah, waktu beredar, manusia bertingkah.
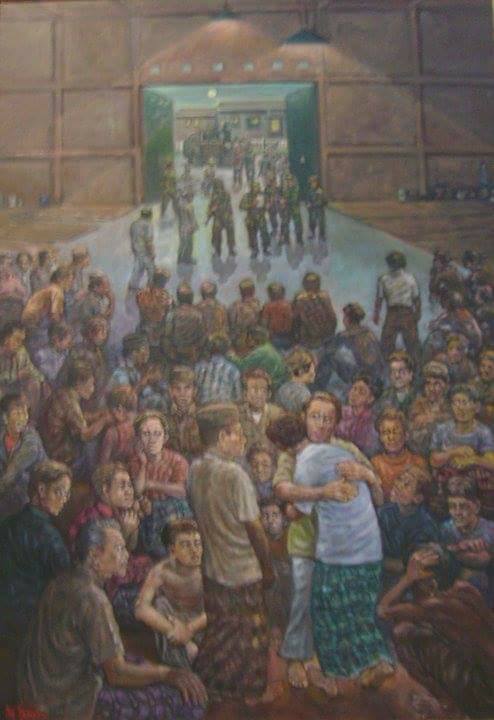
Manusia memang mahluk yang gampang beradaptasi. Jika bisa bertahan dalam setiap peralihan iklim ataupun musim. Dalam keadaan getirpun bisa disenangi. Setelah melalui keterpaksaan tanpa ada jalan lain yang bisa ditempuh.
Kalau begitu enak dong jadi tapol. Biar saja terus ditahan.Tak perlu mengharap bebas. Ah, prinsipnya bukan begitu.
Maksudnya kita harus siap menghadapi kenyataan. Menerima setiap tantangan di mana dan kapanpun juga. Selalu mensyukuri apa yang kita terima sebagai hak milik kita. Jika kita melihat kebawah. Sebab bila kita melihat keatas. Maka kita merasa kurang terus. Alias apes terus. Bisa saja kita akan mengutuk dan menyesali diri kita sendiri.
Demikianlah, semua apa yang telah terjadi harus disikapi dengan pikiran positif. Tergantung dengan pendekatan daya nalar kita sendiri. Jelas kami bersyukur berada di Javahud ini. Sebuah pinggiran pantai kota Banjarmasin. Disekitar tepi sungai Barito yang luas. Dengan air pasang surutnya
yang ditaburi perahu dan kiambang hilir mudik.
Dalam catatan kami, tinggal di Javahud ini. Sebagai tapol yang terasa paling enakan. Ketimbang tempat-tempat lainnya. Menginap dan makan bersama keluarga. Kerja melukis di ruangan agak mewah, guest-house panglima. Bebas pakai tempat ini, asalkan dijaga tetap rapi dan bersih. Kadang ada pula sedikit sekedar uang tip dari penguasa yang cukup berarti. Uniknya, di sini para tapol tanpa pengawal. Mereka hampir seperti orang bebas. Tinggal sedikit bedanya, dari segi status.
Suatu saat di sini saya teringat Tiar yang jauh di udik sana. Boleh juga, tapol bisa berpacaran dengan orang luar. Agak aneh memang. Terutama buat Tiar bodoh amat. Tapi, begitulah manusia, lumbung berbagai lakon dan ulah tingkah yang bermacan-macam.
Cuma, biasanya hal yang semula dianggap aneh, akhirnya bisa tak langgeng. Surat menyurat memang telah berjalan dengan lancar. Walau keluarga saya merasa risi. Tapi karena kasihan dengan kami. Mau saja mereka membantu kami selaku perantara yang setia. Dengan begitu jadilah mereka saksi yang geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Atas terjadinya peristiwa cinta ala “Romeo dan Yulia” di hadapan mata kepala mereka. Rupanya dianggap lucu juga.
Namun, sekali lagi yang luar biasa itu kadang sebenarnya adalah instan. Mudah tergelincir dan terjerembab di jalan yang sudah terniscaya secara alami. Dalam siklus pengalaman sering terjadi. Setiap awal cinta yang bergairah marak menggebu. Selalu dan selalu berakhir dengan airmata perpisahan.
Tadinya saya selaku tapol yang terbelenggu tak berdaya. Telah berupaya melakukan hal-hal yang sewajarnya dibuat oleh orang bebas. Saya kirimi Tiar lukisan-lukisan cat minyak di atas kanvas. Di antaranya lukisan potret dia. Ulangan lukisan hitam putih di atas kertas hasil model poseren tempo hari yang telah saya hafal secara kental dan ngelontok. Tentunya jauh lebih bagus lagi.
Begitu pula surat-surat cinta kami tak bisa dihitung dengan jari lagi. Juga ia saya kirimi buku tebal berisi kumpulan tulisan-tulisan saya. Terutama memuat puisi balada “Tanrangsuli” yang saya tulis di penjara Tabalong sekian tahun jang lalu. Memamg benar kata orang. Bila seseorang jatuh cinta ia akan menjadi penyair yang gila.
Nah, begitulah tiba-tiba suatu hari. Datanglah tanpa diundang berita kejutan dari keluarga saya. Bahwa Tiar telah kawin! Ini, bukan di luar dugaan saya sebelumnya. Malah pernah kubayangkan pula dalam satu dua buah surat saya bagi Tiar. Bahwa jika ada seseorang yang melamarmu. Terima saja, aku siap mengalah. Wong aku bukan orang yang bisa ditunggu. Kapan bebas tak bisa dibayangkan.
Betapapun ia marah, merasa tersinggung oleh kata-kata saya itu, lewat surat balasannya. Buktinya, manusia rentan kembali jatuh ke munafik. Tekad dan janji-janji tak mudah dipegang. Begitu saja selalu gampang menjadi instan dan berubah. Manusia konstan yang setia dengan janjinya. Adalah termasuk luar biasa yang sulit dijumpai. Meski bukan jarang pula terjadi.
Walaupun begitu, tentu terasa menyakitkan. Merasa kehilangan yang dicintai. Siapa tak kan sedih? Tapol pun manusia. Punya rasa cinta dan sedih, jika kehilangan kekasih. Betapapun semestinya seorang tapol dilarang bermain cinta, jika berpikiran waras. Namun, cinta itu buta, kata banyak orang. Tak tahu diri, status kedudukan dan lingkungan sekalipun. Cilakanya, apalagi ini cinta pertama bagi saya.
Dalam nuansa rasa yang tenggelam oleh gelimang kemurungan itu. Lamunan saya kembali terbangun oleh teguran Nyoman Sukerta yang datang menyapa: “Hari sudah mulai gelap, mari kita pulang!” Saya agak tersipu, oleh rasa malu ketanggor oleh kawan saya berasal dari Bali ini. Ia tersenyum, rupanya ia telah menangkap basah. Ketika saya tengah asyik tercenung dalam lamunan yang panjang.
Sejenak saya pura-pura menatap kanvas dihadapan . Yang entah sudah berapa lama kwas ditangan saya terdiam tanpa berkutik sedikitpun. Tampak gambaran di depan saya, jenderal Sobirin Mochtar, panglima Kodam Kalsel, sedang memotong “pantak” (ibaratkan pita dari kayu) dengan parang mandau. Sebagai tanda pembukaan suatu acara seremonial pembangunan gedung pemerintah. Lukisan ini masih dalam tahap finishing.
Lantas saya mengalihkan pandangan saya ke horizon langit senja, dengan bola suryanya yang memancar hampir terbenam. Lewat serambi depan guest-house, tepian sungai Barito semakin tampak menghilang ditelan gelap kelam. Sudiasih dan Nyoman lebih dahulu berjalan di depan saya. Sambil mereka berdua nembicarakan sesuatu.
Mereka berdua pendatang dari kamp pusat penampungan tapol di Liang Anggang. Mereka tadinya dipekerjakan untuk usaha produktif penguasa. Menebang pohon galam dan mengangkut pasir untuk keperluan proyek. Kebebasan bergerak mereka hampir sama dengan disini. Tapi bedanya di sana dikawal puluhan penjaga tapol.
Suatu kekhususan dan keistimewaan di Liang Anggang. Ada beberapa orang tapol yang yang dibolehkan membawa keluarganya hidup kumpul bersama di dalam barak kamp. Bahkan kawan saya Sudiasih sendiri bisa kawin secara resmi di depan penghulu di antara sesama tapol. Selama kumpul dalam tahanan, malah Sudiasih punya anak. Tapi isteri dan anaknya harus tetap tinggal di sana. Tak bisa dibawa kemari. Cuma dengan seizin, setiap minggu Sudiasih bisa menjenguk keluarganya di Liang Anggang.
Kami bertiga, boleh dibilang diuntungkan tinggal disini. Karena profesi dan bakat kami dihargai untuk dimanfaatkan penguasa untuk keperluan apapun. Apakah kepentingan biznis mereka. Kami tak tahu dan tak peduli.
Sementara di Javahud kami bisa menikmati nasib kehidupan tapol dalam kelonggaran relatif terbatas. Entahlah di lain tempat dalam skala nasional. Di tanah air kita yang diliputi chaos dan distorsi peristiwa ’65 ini. Kami bayangkan, mungkin betapa berbedanya terutama di Jawa, Bali dan tempat lainnya yang krusial.
Merebaknya bon-bon tapol dibawa keluar yang tak pernah kembali. Pelenyapan nyawa di ladang-ladang pembantaian. Bangkai mayat-mayat yang bertaburan di pinggir got dan jalan-jalan. Larut di sungai-sungai. Diangkut lewat truk-truk untuk di dom di jurang, lubang sumur tua dan pekuburan massal lainnya.
Semua terdengar melalui getaran suara yang terbawa deru angin yang terpacu dengan arus deras sungai Barito dikala pasangnya. Terkadang lamat-lamat seolah bisikan erang rintihan bersama sedu sedan yang memilukan. Ketika kami memandang terbalut renungan. Kepada kiambang yang larut perlahan di atas permukaan sungai Barito yang mengalir tenang membisu, namun menghanyutkan…..
***
Banjarmasin, awal Februari 2017.
“MEREKA, PARA TAPOL, RAKYAT PEKERJA” (Bagian keduabelas)
Menulis memoar pribadi tentang pengalaman sebagai tapol dari peristiwa ’65 ini. Tanpa ditunjang oleh semangat bertarung melawan lupa. Tak akan selancar seperti biduk (perahu) yang meluncur dengan kencang di atas sungai Barito yang luas ini.
Javahud di kawasan tepian sungai Barito yang permai ini. Jika ditarik melalui dimensi waktu skala sekarang. Ketika saya menuliskannya. Tenyata jauh berubah dari pada dulu.

Kini sungai Barito yang meski tetap ditaburi arakan kiambang dan perahu-perahu seperti dulu. Namun, kini penuh disesaki tongkang-tongkang memuat gunungan batubara yang ditarik kapal kecil yang cukup bertenaga.
Pemandangan seperti ini pernah saya lukiskan dalam suatu karya cat minyak di atas kanvas. Tak berapa lama setelah saya bebas tahun 1978 yang silam. Kini telah terpajang di gedung Pemda Banjarmasin.
Situasinya di skala waktu saya tuliskan cerpen memoar ini. Di saat-saat sistem otonomi daerah telah diberlakukan sejak selama berpuluh tahun. Sesuai dengan banyak ramalan sebelumnya. Berdampak merebaknya raja-raja duit pengusaha batubara. Seperti cendawan tumbuh di musim hujan.
Memang positifnya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan terpacu dengan pesat. Tapi bukan tanpa negatifnya juga. Sebagai akibat krusial dari keserakahan mesin penggerus sistem kapitalisme liberal yang di daerah ini tak lepas teradopsi dengan nyata.
Terutama sangat berdampak terhadap kelestarian lingkungan alam. Dibeberapa kawasan lokasi penggalian batu bara. Seiring dengan kelanjutan penebangan pohon. Baik legal maupun yang ilegal loging, dari banyak perusahaan kayu asing dan domestik.
Penggundulan hutan tropis yang termasuk sebagai salah satu sumber oksigen “paru-paru dunia”. Mengobok-obok! Merangsek mengeruk kedalam rongga jeroan salah satu kawasan tanahair kita yang tercinta ini. Tak kah ibu pertiwi kita menjerit pilu sambil berurai air mata ?
Begitulah sekilas swiping dari tarikan proyeksi waktu di hari ini. Sebelum saya kembali menuliskan lagi jauh keruang memori masa silam pada rangkaian peristiwa ’65. Di tempat ini juga.
Javahud, suatu kawasan di tepian sungai Barito. Di mana bertengger sebuah wisma (guest-house). Milik seorang jenderal, panglima Kodam Kalsel. Yang menjadi tempat tiga orang pelukis tapol ditugaskan penguasa kerja berkarya di sini.
Dekat dari sini, tampak matahari pagi tahun 1970-an. Bagaikan bola kemilau terang benderang menyinari tepat di atas pabrik penggergajian kayu di salah satu celah teluk pinggiran sungai Barito.
Cahaya pijarnya membersit tajam jatuh di otot tengkuk dan punggung-punggung para pekerja tapol. Sedang mendorong gelondongan batang kayu balau yang besar dan berat. Dari tepi sungai kearah kenaikan di dermaga pabrik. Tali temali seling dan katrol silang menyilang dari bawah ke atas. Merupakan garis-garis pengikat yang terbentang berseliwiran di antara tubuh-tubuh telanjang buruh yang mengkilat berminyak oleh semburan keringat.

Saya teringat atas karya saya di tahun-tahun awal kuliah di ASRI Yogya. Jika tak salah sekitar akhir tahun 1961. Tapi, saat itu seingat saya sudah mulai berkiprah di sanggar Bumi Tarung. “Irama Kerja” (Worker rhythm) judulnya yang tak terlupakan. Sebuah lukisan di atas kanvas, dengan warna minimalis hitam-putih. Bergaya post realis yang saya tekuni kembali lewat reuni kepada pembelajaran awal yang lama saya tinggalkan. Tapi masih bernuansa kubistis yang tersisa dari aliran kesukaan saya sebelumnya.
Dalam penulisan cerpen memoar saya ini. Banyak diijelujuri oleh benang merah tentang hakekat kerja dengan berbagai sisi pengertiannya. Karena dari peristiwa ’65 yang saya alami dan jalani. Kerja merupakan garis perjalanan yang panjang yang hampir tak putus-putusnya. Tersimpul dalam gerak jejak langkah dan nafas denyut jantung yang saya hela selama hidup selaku tapol.
Memang kerja bagi manusia adalah syarat mutlak untuk bisa hidup. Buat hidup kita perlu makan. Dan buat makan, setiap mahluk mesti bergerak mendapatkannya. Bagi manusia seba(gai mahluk berakal dan berbudaya. Kerja bukan hanya sekedar menjadi naluri semata. Tapi lebih mulia dan indah.
Karena nilai faedah dan hakekatnya mengandung dinamika dan romantika hidup yang tinggi. Di mana melalui kerja, manusia dapat merubah keadaan dan dunia. Sesuai dengan apa yang diharapkan dan diidamkan oleh mimpi-mimpinya. Baik yang nyata atau yang mungkin. Maupun yang maya (abstrak) atau yang tak mungkin sekalipun.
Namun, bagi saya selaku individu seorang tapol. Kerja dirasakan menyurut drastis secara verbal kepada sisi negatifnya. Ketika porsi konsumsi yang diterima kelewatan log. Diluar batas dosis setimpal yang bisa disandangnya. Oleh suatu kekuatan yang telah menjadi sistem dari kekuasaan. Yang secara paksa menghajatkan korbannya mau tak mau melakukannya. Baik atas dasar dendam ideologis. Maupun kepentingan politik dan ekonomisnya.
Inilah sebagai contoh krusial yang terjadi disetiap zaman. Terutama dialami kita, dalam sejarah. Di zaman kerja paksa Daendels, romusha Jepang. Dan terakhir, seperti apa yang dialami secara langsung oleh saya sendiri. Selaku tapol korban peristiwa ’65 yang dikerjapaksakan pada zaman rezim Orba otoriter berkuasa.
Sudiasih, Nyoman Sukerta dan saya, meski sama-sama tapol yang dipekerjakan, dengan mereka, para buruh pekerja di pabrik penggergajian kayu. Tapi, agak berbeda dalam hal fungsi dan pengerahan tenaga. Memang kerja kami dari segi tenaga agak lebih ringan. Karena faktor profesi, terjadi selisih beban berat dan ringan yang ditanggung diantara kami dengan mereka. Perbedaan ini kadang tergunjing sebagai kesenjangan yang mudah mengundang gesekan (friksi) keiri hatian.
Sebagian di antara kami ada yang menyedari dan memaklumi. Bahwa ada faktor negosiasi yang disikapi secara tenggang menenggang antara kerja badan dan kerja otak. Dalam arti jika kami dianggap punya beban amat ringan dari segi kerja badan. Kerja otak yang kami kerahkan sebagai kelebihan ilmu profesi yang kami peroleh dari sekian tahun pendidikan. Ini sebagian dapat menerimanya secara legowo.
Soal ini kadang begitu peka di kalangan para tapol yang dipekerjakan. Justeru sebagai dampak dari status di kerja-paksakan oleh penguasa.
Dalam teori dikatakan, bahwa dalam masyarakat sosialis. Orang bekerja berdasarkan kemampuannya dan mendapat upah sesuai dengan hasil kerjanya. Sedangkan pada masyarakat kapitalis, betapapun siburuh mengerahkan kerja badannya sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Belum tentu ia mendapat upah sesuai dengan hasil kerjanya.
Sehingga di sini kesenjangan di antara kerja badan dan kerja otak semakin tajam. Bukan hanya karena secara langsung majikan atau pemodal menarik keuntungan lewat nilai lebih dari jam kerja yang memeras keringat kaum buruh. Malainkan justeru melalui ulah kerja otak, maka terjadilah permainan untuk menuai keuntungan (profit) bagi pemodal terhadap hasil kerja badan kaum buruh dalam proses produksi.
Masalah yang timbul berkenaan tempat tinggal kami bertiga telah tergabung bersama para tapol buruh pabrik penggergajian kayu.. Dalam satu komplekperumahan yang tak jauh dari pabrik, di mana mereka dipekerjakan.
Kami tinggal bersama keluarga pak Ngalimun, montir ahli mesin yang sangat diperlukan oleh pabrik. Ia ditahan karena dituduh sebagai anggota pengurus ormas buruh Sobsi. Isterinya anggota aktivis Gerwani yg sudah lama dibebaskan. Anak-anak mereka berlima Tuti, Iyul, Onie, Endang dancam Djoko. Keempat anak tinggal bersama mereka. Sedangkan seorang lainnya yang sulung Tuty, selaku perawat tinggal di asrama.
Bagi kami bertiga, pak Ngalimun yang tampak kebapaan. Bersama isterinya yang juga keibuan. Benar-benar semacam induk semang yang sangat baik. Pendekatan kepada kami, mereka berdua bersikap layaknya orang tua yang mengasuh kami. Tak ada bedanya, terhadap anak-anak mereka sendiri. Tanpa sama sekali memperlakukan dan melayani kami sebagai teman setapol.
Nah, saking merasuknya kekeluargaan diantara kami. Sehingga terhadap keempat anak mereka. Kami merasa tak ubahnya sebagai adik-adik kami sendiri yang amat akrab. Sedangkan Tuty selaku anak tertua yang lebih dewasa. Rata-rata sekali seminggu datang berkunjung dari asrama, menjenguk keluarganya di Javahud.
Alkisah tercerita tentang Tiar, yang masih timbul tenggelam namanya dalam ingatan pahit dan getir saya. Kenangan indah dari padanya terkadang saja menyelinap lewat lamunan saja. Saya telah lama berupaya untuk melupakannya. Bagaimanapun, saya tak bisa menganggapnya khianat atas cinta kami. Wong sudah berkali-kali saya nyatakan kepadanya: tinggalkan saja saya! Aku orang yang tak bisa ditunggu kapan bebas. Tanpa ada harapan.
Namun, kehilangan cinta tak hanya sekedar tinggal sebuah lagu ratapan nelangsa dinyanyikan oleh seorang yang patah hati. Tapi terasakan suatu suasana hampa dan sepi. Ibarat kanvas kosong kehilangan bentuk dan warna.
Betapapun seorang tapol yang secara sadar, semestinya bersikap tegar menghadapinya. Demi teruji oleh yang jauh lebih parah sekalipun, telah terlewati. Tapi keterenyuhan hati terlibas cinta pertama sukar untuk ternetralisir dari kenangannya begitu saja.
Untung saja kedua teman saya Sudi dan Nyoman, dapat memaklumi. Untuk mengalihkan perhatian saya kepada hal-hal yang positif. Melalui berbagai dialog bermakna di samping kelakar yang ceria. Dari pada terbenam dalam lamunan rasa stres yang sia-sia tak berguna. Meski dengan upaya menenggelamkan diri ke kesibukan berkarya. Tak selalu mempan menghilangkan dan melupakannya.

Nah, pada saat-saat waktu berkelindan dalam gelimang rasa kehilangan yang hampa dan sepi itu. Kebetulan anak sulung pak Ngalimun, Tuty. Di setiap pekan semakin lebih sering mengunjungi keluarganya di Javahud. Hanya karena membawa rundungan nasib yang hampir sama sebangun dengan pengalaman luka di hati saya, kehilangan kekasih.
Mungkin tak serupanya, cuma rasa kehilangan yang menerpa Tuty masih bersifat menggantung. Namun, bayangkan! Apa arti bu Ngalimun menyuruh saya membuatkan lukisan potret Tuty pada awalnya, tanpa setahu orangnya sendiri ? Ah, gampang diduga. Sang ibu, kemungkinan kuat sengaja menggatukkan saya dengan anak sulungnya. Justeru ia tahu dan marah kepada pacarnya Tuty yang memperlakukan anaknya dengan berselingkuh kepada perempuan lain. Sehingga saya mau dijadikan bumper untuk pelarian pembalasan dendam anaknya.
Semuanya telah terungkap dari uraian curhat Tuty sendiri kemudian. Pada beberapa kali temu kangen kami. Yang cukup terdorong lebih mengarah kepada harapan ibunya. Untuk menggatukkan kami berdua, sesuai dengan dugaan saya semula.
Saya dapat memahami dan merasakan pula, jika bu Ngalimun punya perhatian khusus dan niat baik terhadap saya. Beliau sering menunjukkan rasa kasihan dan prihatin atas pengalaman putus cinta yang menerpa diri saya selama ini. Ternyata dalam prosesnya yang berkelindan. Bukan saja hanya terdorong oleh keinginan saya untuk memenuhi kehendak dan harapan beliau yang saya hormati. Tapi pendekatan di antara kami dari hati( kehati. Telah merupakan sambung rasa dari sublimasi pelarian dari nasib kami yang sama.
Apa yang terjadi selanjutnya ? Tentu sulit di sini untuk dilukiskan dengan kata-kata. Dapat dibayangkan saja. Ungkapan suatu pertanda yang terselubung. Dibalik kata “pelarian” cinta yang terbakar api dendam. Akan membuka adegan demi adegan romantis yang terlarang. Dari peristiwa di bawah satu atap rumah. Memayungi sebuah keluarga besar tapol yang guyub dalam kebersamaan menanggung duka derita zaman.
Romantika sekejap disekilas peristiwa. Dari lika-liku kehidupan manusia yang terbelenggu gerak hidupnya oleh kekuasaan suatu rezim. Bagi saya pernah telah memberikan berkah untuk seseorang anggota keluarga tapol senasib yang amat saya hormati.
Tuty, anak sulung perempuan pak Ngalimun. Kembali dirujuk oleh pacarnya semula untuk segera ia nikahi. Hanya karena ia tahu. Dari pada digaet oleh seorang tapol lewat selingkuh.
Matahari kemarau bagaikan bola merah yang pijar mendaki langit. Semakin membuat panas terik membakar otot-otot punggung dan bahu para buruh tapol, pekerja pabrik penggergajian kayu. Mereka telah selesai menaikkan sebuah gelondongan batang kayu yang besar di tepi sungai Barito.. Hampir memakan waktu setengah hari penuh.
Kamipun bertiga bersiap berbenah untuk istirahat jeda tengah hari. Dari pintu belakang guest-house saya memandang dari jauh kearah komplek hunian kami. Beriringan dengan langkah berat di bawah panas terik, belasan buruh tapol pekerja pabrik menuju pulang.
Sebelum kami menyusul mereka, sejenak saya melepas nafas lega, sambil menatap tempat tinggal kami. Bahwa di sana tak ada beban moral lagi yang disangga dan dipikul oleh keluarga besar pak Ngalimun. Sebab semua sudah tuntas. Berkat penyelesaian kontradiksi yang lugas dan benar. Apapun pengorbanannya. Sebagai tugas manusia yang mulia…..
***
Banjarmasin, awal Februari 2017
“KIAMBANG BERTAUT, LARUT KE HULU” (Bagian Ketiga belas)
Kehilangan kebebasan sebagai hak azasi warga negara, bagi para tapol adalah suatu musibah atau tragedi yang menyakitkan. Tetapi terlebih lagi secara psikologis. Terasa amat menderita. Ketika mereka diceraikan atau dipisahkan secara terpaksa dengan keluarganya. Ini saya khayati lewat pengalaman langsung setelah menjalaninya.
Barangkali karena di samping sudah tentu mereka sedih oleh terlepasnya kontak kedekatan diri bersama keluarganya.Ternyata yang jauh lebih menyakitkan lagi, tatkala daya nalarnya tergandakan oleh penderitaan keluarganya yang mereka tinggalkan.
Ini terutama saya rasakan dan lihat sendiri, lewat kasat mata. Bagi kawan-kawan yang sudah berkeluarga. Dalam arti punya bini dan anak-anaknya. Apalagi yang beranak pinak banyak sebagai tanggungannya.
Saya selaku tapol lajangan tentu agak berbeda dengan mereka. Walaupun saya juga punya keluarga. Ibu, ayah adik dan kakak yang tentu saja turut sedih dan prihatin terhadap nasib saya masuk tahanan. Atau paling tidak, hanya pengalaman gagal cinta yang terniscaya oleh keadaan. Risikonya relatif biasa untuk bisa lebih gampang terlupakan. Namun, bagi mereka atas dasar tanggungjawab selaku pemikul beban utama keluarga, itulah kelebihannya.
Sering saya temukan disetiap curhat mereka. Jika teringat soal ini, mereka bercerita tanpa bisa menahan air mata. Bukan hanya dialami oleh bagi mereka pasangan lama yang telah banyak anak sebagai tanggungannya. Bahkan, ternyata juga menimpa kepada pasangan yang lebih muda. Termasuk mereka yang baru kawin.
Kasusnya kebanyakan rata-rata isterinya minta cerai. Oleh sebab berbagai faktor. Terbanyak karena rasa trauma. Di antaranya juga oleh isu-isu yang dibuat orang tertentu, termasuk aparat sendiri. Yang memanfaatkan kesempatan memancing di air keruh. Untuk menggaet pasangan sang korban. Yang ditinggalkan karena ditahan dalam waktu tak terukur.
Di sanalah kepahitgetiran secara psikologis yang paling parah yang diderita para tapol. Selaku korban peristiwa ’65 yang masih hidup. Minus mereka yang menjadi korban pelenyapan nyawa secara brutal tanpa keadilan. Melalui berbagai kekejaman tindak pelanggaran berat hak azasi manusia.
Namun, terjadi pula hal yang sebenarnya cukup mengharukan. Betapapun penguasa tak melarang. Bagi para tapol yang terpaksa menyeret anak isterinya hidup bersama dalam barak tahanan. Sebagai alternatif upaya lainnya. Karena dimungkinkan bagi sitapol untuk mencari nafkah sendiri dibantu keluarganya. Di samping memenuhi syarat keharusan kerja paksa dari penguasa.
Ini kebanyakan menerpa bagi keluarganya yang tak mampu bertahan. Ketika ditinggalkan, tanpa peran tanggung jawab sang tapol sendiri sebagai kepala keluarga. Bayangkan! Berarti betapa banyak anggota warga negara kita yang ditahan bersama seluruh keluaganya. Bukankah hal ini merupakan kekisruhan chaos anggota warga negaranya yang menjadi tanggungjawab rejim yang berkuasa?
Secara karakteristik, sebagai contoh yang menimpa keluarga pak Ngalimun. “Induksemang” yang kami tinggali di Javahud. Memang sekali-sekali pak Ngalimun selaku ahli mesin tapol yang dimanfaatkan penguasa. Mendapat sekedar insentip dari pabrik. Tapi jauh dari mencukupi. Untuk menanggung enam orang keluarganya.
Nah, terpaksa peran bu Ngalimun banting tulang bekerja selaku penjual sayur. Mulai sejak subuh pagi-pagi buta, bu Ngalimun berangkat naik sepeda kepasar sayur untuk berbelanja bahan jualannya. Kemudian sekitar setengah harian ia menjajakan sayur barang jualannya kemana-mana. Kemudian ia pulang membawa serba sedikit bahan masakan buat makanan sarapan keluaganya. Termasuk buat kami bertiga. Dari hasil keuntungan usaha dagangannya.
Tentu saja kami bertiga yang tinggal bersama keluarga pak Ngalimun. Turut memperhatikan beban hidup sehari-hari mereka. Setiap insentip yang kami dapat dari penguasa. Masing-masing kami telah menyisihkan porsi buat membantu keluarga pak Ngalimun. Meski bukan dalam wujud harga bayar makan atau sewa rumah. Tapi turun naik berdasarkan kemampuan kami yang ada. Terkadang kurang atau malah lebihan.
Kesimpulannya karena kami saling menganggap keluarga. Maka keluarga Ngalimun bersikap selalu relatif baik, ramah dan senang terhadap kami. Melebihi dari perasaan senasib dan sependeritaan sebagai tapol.
Apalagi setelah terjadi penyelesaian yang bijak dari persoalan “kasus Tuty”, anak sulung perempuan pak Ngalimun. Mereka, terutama bu Ngalimun semakin menenggang rasa (toleran) dan menaruh hormat terhadap saya. Kayaknya gengsi saya terangkat di hadapan mereka. Karena sikap kebijakan dan pengorbanan saya yang bersifat realistis. Tanpa rasa kecewa yang saya tampilkan. Di mana, tadinya mereka cemaskan. Akibat dampak keterlanjuran Bu Ngalimun mendorong dengan sengaja berkonspirasi dengan anaknya untuk menjalin hubungan intim dengan saya sebagai pelarian.
Padahal saya tak munafik. Bukan tidak ada, suatu nuansa hasrat “menyukai” dalam perasaan saya terhadap anak gadisnya. Ini saya akui secara terus terang kepada seluruh keluarga. Tidak hanya sekedar sahabat atau “adik saudari” yang bersifat kekeluargaan saja.
Sedangkan ternyata Tuty merespon lebih aktif sedemikian rupa, di luar dugaan saya. Meski terbaca dari ucapan dan gestur tubuhnya, tak lepas dari kecurigaan saya. Bahwa sangat dimungkinkan tingkah polahnya sebagai ekspresi dari niat pelarian atas rasa dendam kesumat terhadap pacarnya.
Bagaimana dapat menghindarkan ? Tatkala peluang datang yang jelas direkayasa. Dan mendapat restu oleh berbagai sudut dan pihak yang berkehendak, ternyata dari seluruh keluarga. Hingga ibaratnya, atap rumah yang di ataspun terurak bagaikan payung penyungkup. Bersiap untuk menaungi dan melindungi dalam keadaan terjaga. Untuk kami berdua! Apapun bisa kami perbuat dengan bebas.
Hanya berkat akal sehat dan daya nalar dari kebijakan pikiran dewasa yang terukur. Hubungan intim yang romantis penuh pelepasan hasrat pelarian. Tidak sampai terjerumus atau terjebak kedalam perangkap kemesuman yang terlarang.
Justeru dalam momen puncak dari gairah nafsu manusiawi berdasarkan kodrat mahluk alamiah. Dibawah sinar lampu tidur 5 watt yang temaram. Maka tersentak telusur ingatan saya membuntu pada batas jangkar kesedaran sesaat yang kembali membumi. Bahwa ini adalah pelampiasan rangsang pelarian dendam liar tak terkendali yang berbahaya. Harus kita stop!
Saya bangkit berdiri, dan menarik tirai gordin untuk membuka pintu kamar kami. Yang sejak beberapa jam yang lalu ditinggalkan kedua kawan saya. Sambil melihat ke wajah Tuty yang nelangsa, diterangi sinar lampu dari luar kamar. Saya memberikan isyarat kepadanya, sambil menggelengkan kepala kearah kamar keluarganya.
Sayapun turun keluar rumah sekedar melepas rasa gerah yang cukup lama terperam di dalam kamar. Untuk menghirup udara berangin malam yang bertiup sepoi. Bulan sabit tergantung tegak lurus persis menjulang di atas atap bubungan pabrik penggergajian kayu. Bagaikan sepotong pijar cahaya berbentuk irisan semangka yang tersisa.
Sungai Barito diwaktu malam terpendar dalam kegelapan. Samar-samar tampak iringan kiambang bertaut larut kehulu. Bayangkan! Ini hal yang muskil. Bertentangan dengan kodrat keharusan air sungai yang selalu mengalir kehilir.
Namun disini, salah satu perkecualian. Di antara banyak kekhususan lainnya. Sungai Barito kala surutnya, iringan kiambang memang bertaut larut ke hilir. Karena dekat dengan laut. Maka pada masa pasangnya ia kembali hanyut ke hulu. Bagaikan “arus balik” salah satu judul novel Pram yang ditulisnya di kamp gulak tropis Pulau Buru.

Di malam berbulan sabit yang temaram ini, kusaksikan diatas permukaan sungai Barito. Kiambang bertaut, larut ke hulu. Ini tidak lazim seperti yang sering kami lihat di sungai-sungai sekitar kamp Hulu Sungai Utara. Nah, andaikan bisa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana caranya buat menarik tali simpul untuk diputuskan ?
Dari jauh sayup-sayup terdengar berdentang bunyi lonceng waktu sepuluh kali. Kedua kawan saya, Sudi dan Nyoman masih belum pulang. Mereka pergi, hanya sekedar memberi kesempatan kepada kami. Tuty dan saya untuk berkencan dengan tenang, bebas gangguan. Apa tak salah, seorang tapol bisa berkencan di dalam tahanan ? Inikah semacam hal yang tak mungkin menjadi mungkin ? Layaknya arus balik. Seperti kiambang bertaut. Yang larut dari hilir ke hulu ?
Malam itu saya telah menghabiskan waktu sekitar setengah jam berada diluar rumah. Merenungkan dilema persoalan tentang nasib manusia yang telah menjadi tantangan klasik. Setelah saya kembali ke kamar kami,Tuty sudah tidak berada lagi di sana. Hingga pagi esok harinya, kami tak sempat lagi berjumpa. Ia meninggalkan rumah pagi-pagi buta, tanpa pamit samasekali dengan kami.
Melalui Bu Ngalimun pesan Tuty disampaikan. Bahwa ia menyatakan maaf, tak sempat pamit. Karena mengejar waktu untuk mengikuti apel pagi di asrama.
Sampai sebulan lebih ia tak pernah menjenguk keluarganya di Javahud. Hingga kami mendengar berita lewat bu Ngalimun tentang rencana pernikahan Tuty dengan pacarnya.
Duduk perkaranya lebih jelas terurai lewat curhat bu Ngalimun kepada saya. Beliau merasa sangat berterima kasih atas sikap saya yang dapat memahami secara bijak terhadap keadaan Tuty.
Menurut pendapat beliau. Justeru karena ditunjang oleh peran kedekatan Tuty dengan saya.Yang akhirnya diketahui oleh pacarnya Tuty. Sehingga membangkitkan kecemburuan yang memicu niatnya untuk pemulihan kembali hubungan mereka yang tadinya sementara terputus. Mereka berdua berpacaran cukup lama, sekitar tiga tahun. Dalam status sama-sama perawat.
Demikianlah perjalanan salah seorang anak manusia, menapak petualangan asmara yang getir tapi indah. Dari kehidupan nasibnya yang tangguh berkelindan di antara rantai belenggu yang berlika-liku.
Mulai sejak mengenal bunga eksotis Tanrangsuli yang tumbuh sunyi di relung belukar dan belantara hutan pegunungan Meratus. Lantas menuruni tebingnya yang landai. Tersinggah dipersimpangan tiga Silongan, bersua dengan Tiar yang manja. Hingga larut ke hulu. Beriring kiambang tertaut diatas permukaan sungai Barito di Javahud. Menyapa sekilas kepada Tuty, puteri sulung seorang bapak buruh tapol, pecinta kerja yang berwibawa. Tergurat di album kenangan awal nama “3 huruf T” mereka, sahabat rakyat pekerja: Tanrangsuli, Tiar dan Tuty yang tak terlupakan…….
***
Banjarmasin, medio Februari 2017
“KAMAJAYA” (Bagian ke empat belas).
Ketenangan melangut dalam kesunyian, dari air sungai Barito yang mengalir perlahan kehulu. Tak kan lama juga berkisar bersama kami. Sekitar belum sampai setahun kami berada di sini.
Suasana demikian yang telah melekat dalam naluri kami selama ini. Akan pudar tinggal kenangan. Javahud, selamat tinggal! Kami meninggalkanmu, bukanlah oleh kehendak kami sendiri. Kau tahu, lagi-lagi kami terenggutkan!
Ada tangan kekuasaan yang kekar lebih keras dari baja. Selalu terjaga di kala kau bangun dari tidurmu. Lantas menarik dirimu kemanapun yang dia mau. Kau tak bisa menolak dan meronta. Ketika dia merenggutmu dengan keras dari oase ikatan silaturahmimu yang intim dan akrab, dengan keluarga pak Ngalimun yang baik.
Tangan perenggut yang kekar itu. Bukan tangan seseram preman jagal yang bertatto atau bergelang akar bahar. Bahkan lebih kuat dan bengis dari kran buldozer yang sekali tarik kau akan terangkat lalu terlontar entah kemana. Dia memang merupakan kekuatan maya (abstrak) yang amat menentukan dirimu. Tak berbentuk, tapi berduduk di atas tahta dan sistemnya. Perintahnya tanpa bisa kau tolak atau ditunda dengan cara apapun. Itulah yang namanya “kekuasaan”!.
Tapi kami telah terbiasa, wong namanya tapol, tahanan politik. Secara rutin bagaikan bola pimpong, ditukar pindahkan. Kemanapun kehendak penguasa. Bahkan siap untuk ditendang atau digebuk, tanpa melawan. Seperti yang banyak terjadi selama ini. Menjadi bulan-bulanan sarapan pagi, siang dan malam dari bal-balan tendangan dan gamparan mereka.
Maka, diberangkatkanlah kami bertiga, Sudi, Nyoman dan saya meninggalkan Javahud. Naik mobil pick-up tua, dengan hanya seorang pengawal. Tak banyak barang yang kami bawa. Karya lukisan dan ukiran kayu, semua disuruh tinggal oleh petugas di Guest-house. Karena itu dianggap milik Pemda alias punya Pangdam. Tapi alat-alat kerja dari kwas hingga bahan cat-catan, terutama cat tube yang berharga mahal, boleh kami bawa.
Entah kemana kami dibawa atau dipindahkan ? Tapol rupanya pantang diberi tahu. Kepindahan tapol selalu dadakan dan terburu-buru. Sehingga kami tak sempat pamit dengan keluarga Ngalimun sepagi itu. Pak Ngalimun sendiri sedang kerja dipabrik. Ibu, sang isteri, jualan sayur. Dan anak-anak pergi sekolah.
Anggapan kami selama ini, selaku tapol yang dipekerjakan di Javahud inilah yang terasa paling longgar dan enak. Terutama dari segi kekawanan dan kekeluargaan. Bahkan uniknya tanpa pengawal secara langsung. Kami bisa berkarya dengan kemandirian. Asalkan ingat tanggung jawab kerja dan status kita.
Nah, sekarang kami dibawa kemana? Apakah akan kembali di sangkarkan dalam ketidakbebasan yang ketat. Seperti disaat-saat awal penahanan dulu? Ah, rasanya tidaklah. Berdasarkan logika pengalaman, tentu situasi kian lama semakin longgar. Tak ada alasan pemerintah untuk memperketat. Apalagi selama ini kami telah terpercaya dan teruji bekerja tanpa pengawalan. Tanpa ada kasus yang bisa dipermasalahkan.
Namun, dari segi sekurity, tapol sudah biasa diperlakukan selaku korban yang diliputi teka-teki pertanyaan dek-dekan dan perasaan traumatis. Sebab dari ukuran politik kekuasaan, tapol dianggap sebagai musuh negara. Rasa was-was seperti itu agaknya sudah lewat. Hingga tak terasa, mobil yang kami tumpangi telah tiba di depan bioskop “Kamajaya”. Setelah barang-barang kami turunkan. Lantas kami digiring ke belakang bioskop, menuju barak tempat kami dimukimkan.
Seorang letnan CPM yang selama ini telah kami kenal bernama Abdulsamad, menyambut kami. Dia adalah pelaksana lapangan yang mengurusi “pemanfaatan” seluruh tapol di Kalsel buat keperluan usaha produktif Pemda. Ia seorang petugas yang keras dan disegani. Untuk tak dikatakan paling di takuti oleh para tapol. Sedangkan komando puncaknya berada ditangan Letkol Ali Inderajaya. Seorang pimpinan militer yang sangat berwibawa. Ia berkantor di suatu ruang khusus bioskop Kamajaya. Sebagai manager top yang mengatur keberadaan usaha produktif daerah militer Kalsel ini.
Nah, suasana dan situasi di sini, memang jauh berbeda dengan di Javahud. Di pinggiran sungai Barito itu, meski ada bunyi raungan mesin penggergajian kayu setiap hari, tapi di sana relatif tenang dan santai. Tapi di sini, suasana ramai dan gaduh dari suara orang dan bunyi musik film yang bising, selalu setiap jam kita dengar.
Dan kerja kami jauh lebih keras dan berat di sini, ketimbang dengan di Javahud. Padat dan sibuk sekali tugas kami. Bahkan sangat luar biasa. Di samping membuat dekorasi di kiri kanan panggung layar bioskop, merupakan relief pahatan batu. Juga yang lebih berat menguras tenaga, ialah membuat baliho poster reklame film.
Buat menangani tugas yang secara rutin ini, sebuah tim kerja dibentuk. Semua dari tenaga tapol. Bagian pekerjaan kami bertiga, Sudi, Nyoman dan saya, terutama khusus melukis dari foto reklame film di atas hardboard. Sesudah itu, ada bagian pemotongan dan pemasangan di atas puncak bubungan tinggi gedung bioskop Kamajaya. Ini tugas paling berat dan berbahaya.
Tapi begitulah, apapun tantangan kerja yang kami hadapi selaku tapol. Seberat atau serumit apa saja, kami sudah terbiasa beradaptasi mengatasinya.
Selain itu, kami bertiga membuat dekorasi panggung relief dari bahan batu cadas yang dipahat. Tema dan motifnya, di sebelah kiri penari Bali. Sedangkan di kanan Srikandi belajar memanah dengan Arjuna.
Konsep temanya berasal dari ide pak Ali Inderajaya. Seorang penggemar cerita pewayangan. Sedangkan kami hanya menuangkannya dalam bentuk seni dan artistiknya saja.
Nama bioskop Kamajaya juga diciptakan oleh letkol CPM yang peramah dan pecinta seni ini. Dalam cerita pewayangan, Kamajaya adalah seorang tokoh dewa yang elok rupawan. Anak kelahiran pasangan Semar dan Dewi Sri. Ia kawin dengan dewi Kamaratih yang cantik. Keduanya merupakan lambang (menurut kepercayaan agama Hindu) dewa kebahagian, kesejahteraan, dan keselamatan umat manusia.
Pokoknya betapapun keras dan berat kerja kami di sini. Kami sudah terlatih untuk menyenangi hal-hal yang getir dan pahit. Apalagi kami tinggal berada di sekitar bioskop. Hiburan tatapan mata tak kurang-kurang adanya. Para tapol yang siang malam telah kerja keras. Terkadang sekali-sekali dibolehkan juga ikut menonton. Jika ada waktu kesempatannya. Tapi bagi kami para penggemar film. Disela kelelahan habis kerja keraspun, masih mau duduk bertahan menonton sambil rehat. Bila kebetulan yang diputar film yang sangat disenangi.
Seingat saya ada 2 film “barat” jaman dulu (jadul) yang sempat saya lihat di sini, yang cukup berkesan bagi pribadi saya. Pertama, “Waterloo Bridge” yang dibintangi Robert Taylor dan Vivien Leigh, tentang ketegaran dan kesetiaan cinta manusia dalam menghadapi tantangan perang. Kedua, “Casablanca” film romantis yang diperankan bintang film tersohor Humprey Bogart dan Indrid Bergman. Melukiskan kepedihan duka dan rindu seseorang. Ditenggelamkan oleh nemori rasa kehilangan yang tak berujung atas buah hatinya.
Begitulah, ada keterkaitan sentuhan rasa dari sesuatu yang kita lihat dan temukan. Dengan pengalaman pribadi yang terpendam, setelah kita lalui. Apakah ini bagian dari perasaan terenyuh burjuasi kecil yang tak terhindarkan meretas hati manusia ?
Sebenarnya tidak semua film-film barat atau hollywood, jelek, vulgar atau hedonis. Betapapun dulu sebelum peristiwa ’65, kaum progresif-revolusioner, secara politik sangat menentang dan menolaknya. Karena alasan sebagai sumber produk kekerasan, rasialisme, pornografis dan lain-lain.
Tapi dari 2 film barat yang sempat saya tonton itu, ternyata cukup bagus. Iya, ini memang berdasarkan penilaian subyektif orang perorangan. Bukan dalam libatan isu politik sesaat yang pernah tercetus di masa konflik “perang dingin” yang silam.
Bicara mengenai film, bukanlah atas dasar pandangan partisan. Bila sesungguhnya film produk dari negara sosialis seperti misalkan “Potemkin” karya sutradara film Rusia Sergei Eisenstein merupakan film terbaik dunia sepanjang zaman. Saya pernah sempat menontonnya semasa sebelum peristiwa ’65. Memang hebat dan luar biasa.
Tema film “Potemkin” melukiskan tentang situasi menjelang awal revolusi Oktober 1917, terjadi pemberontakan kelasi di atas kapal Potemkin sebagai letikan api pertama dari sumbu perjuangan revolusioner, terutama oleh kaum buruh dipimpin proletariat Bolsyewik. Untuk menumbangkam kekuasaan monarchi Tsar Nicholas II.
Seperti pula dalam sejarah perjuangan kita melawan penjajahan kolonialis Belanda. Yaitu di peristiwa pemberontakan “Kapal tujuh” (Zeven Provinsien) pada tahun 1933.
Jadi, film Potemkin saya kagumi, bukan hanya karena temanya yang hebat. Tapi juga dari sisi cinematografi dan artistik seni celluloidnya yang luar biasa.
Di bioskop Kamajaya, memang para tapol benar-benar dikerjapaksakan dengan keras dan berat. Durasi waktunya sejak pagi hingga tengah malam, bahkan kadang sampai subuh. Karena selalu spot bekerja serba cepat, sesuai dengan jadwal pemutaran film yang terus secara rutin, kontinyu dan simultan.
Sehingga ternyata berdampak kepada kondisi kesehatan para pekerja tapol. Ada beberapa orang, termasuk kawan saya Sudiasih. Muntah darah, kambuh tbcnya. Untung saja sang manager pak Ali Inderajaya sangat peduli dan penuh perhatian. Mereka yang sakit diistirahatkan dan disuruh ke dokter buat pengobatan.
Di antara catatan harian saya yang belakangan ini jarang-jarang terisi. Sempat ada tercatat, bahwa masa tahanan kami tak terasa sudah mendekati satu dekade. Hampir puluhan tahun, resminya terpasung atau terbelenggu dalam tahanan. Tapi itu yang tersurat. Tersiratnya, terasa seperti halnya pula layaknya orang bebas. Dari segi gerak hidup kami. Paling kadang terasa cuma sebelah kaki yang terikat di dalam. Itulah yang mungkin masih tertinggal hanya status kami. Karena apa?
Bukan hanya karena kian lama semakin longgar diberikan hak bergerak oleh penguasa. Secara sedikit demi sedikit. Tapi terutama lantaran oleh peran aktif kesedaran subyektif secara maksimal dari kami sendiri. Dalam membuka ruang gerak kami sendiri. Setapak demi setapak mengayun jejak langkah untuk berdialog. Mendekati mereka orang bebas. Serta bersentuhan dengan masyarakat.
Tapi ternyata dalam prakteknya tak selalu dengan mudah. Atau gampang-gampang saja. Buktinya, sebagai contoh. Di bagian samping gedung Kamajaya, bermukim beberapa orang seniman bebas, tinggal guyub dalam “Sanggar Budaya” nya yang dipimpin oleh seorang dramawan dan pelukis Adjim Ariyadi. Anehnya, katatakanlah sementara waktu yang relatif cukup lama, kami tak saling bertegur sapa. Meski kami sering saling berpapasan, di antara kesibukan kerja kami masing-masing. Padahal kami tinggal berada di bawah naungan satu atap gedung.
Nah, ini adalah suatu masalah yang masih dilematis saat itu. Dalam kaitan dengan atmosfer situasi politik dan ideologi negara yang mengiklimi kehidupan warga masyarakatnya selama ini. Nuansa otoriter suatu rezim, masih bergeming dengan kekuasaannya. Untuk tak sedikitpun menurunkan tensi represinya dari garis batas de markasi yang sudah selama satu dekade ditancapkan. Tanpa ada solusi negara secara resmi yang mengajak berdamai dalam suatu rujuk nasional hingga merata turun kebawah. Apalagi lebih jauh lagi, jika rekonsiliasi sebagai pilihan. Padahal peristiwa ’65 sudah hampir 10 tahun berlalu.
Mereka enggan dan segan melanggar garis batas terlarang itu. Ada rasa gamang dan alergi di pihak mereka. Apalagi halnya terhadap kami. Bagaikan pengidap penyakit lepra yang terpaksa mengisolasi diri dalam karantina gerak-gerik kami. Agar orang lain pantang menjadi korban terjangkiti tularannya.
Kisah tentang konflik antara Lekra dan Manikebu tinggal trauma yang masih sulit terhapus. Betapa kuatnya rezim Orde Baru lewat doktrin “bersih lingkungan” mengkondisikan masyarakatnya. Sehingga masih bersikap layaknya menganggap musuh. Terhadap suatu golongan warga negara yang nasibnya sama dengan kami para tapol.
Sekitar 4 tahun yang lalu, kami masih ingat selaku tapol yang sedang dipekerjakan di luar. Telah dapat mengakses informasi berita pada pertengahan 1970. Bahwa Bung Karno wafat dalam keadaan mengenaskan.
Betapa tragis penderitaannya selama hidup terisolasi di rumah tahanan Wisma Yaso. Sulit untuk diterima oleh daya nalar kami. Almarhum selaku founding father, presiden pertama kebanggaan rakyat Indonesia. Serta tokoh proklamator kemerdekaan kita. Kenapa jenderal Suharto yang tadinya pengabdi bawahannya yang setia, begitu tega memperlakukannya dengan kejam?
Kini, kembali kami dapat menyimak situasi politik. Ketika mulai menemukan gilirannya. Atas perbuatan pelengseran dari semacam kudeta merayap atau merangkak. Atas kepemimpinan sejati yang tak pernah redup dan pudar dalam sejarah.
Kami sebagai saksi imajiner. Ketika sinar matahari 15 Januari 1974 memanggang para tapol yang sedang dipekerjakan memasang baliho sebuah film laga. Di atas bubungan atap gedung bioskop Kamajaya.
Ternyata pada hari itu, matahari yang sama terpendar cahayanya di balik kepulan asap yang membubung tinggi mencakar langit Jakarta.
Itulah pertanda visual secara imajiner atas gambaran latar belakang (background) peristiwa Malari yang meletus. Bagaikan letikan api yang membakar padang ilalang kekuasaan rezim Orde Baru yang otoriter. Setelah berusia hampir satu dekade.
Ini bukanlah bayang-bayang kelam dari sebuah karma. Yang muncul melalui perbuatan konspirasi jahat dengan siluman asing, dalam suatu perebutan kekuasaan yang inkonstitusional. Melainkan karena dampak sistem ekonomi dari kekuasaan otoriter Orba Suharto membuka kran modal dan investasi asing seleluasa mungkin. Sehingga barang-barang impor terutama dari Jepang, masuk membeludak membanjiri tanah air kita, tanpa kendali.
Buat pertama kali, lewat peristiwa Malari, bangkit massa rakyat. Terutama oleh kaum intelektual dan barisan mahasiswa melakukan perlawanan melalui aksi-aksi demontrasi terhadap rezim Orde Baru.
Meski dapat dipadamkan secara represif oleh penguasa. Namun, ini cetusan awal permulaan yang akan memicu dan memacu inspirasi bagi kebangkitan perlawanan berikutnya menuju kemenangan.
Matahari Januari 1974 semakin naik menanjak. Sementara kami para tapol telah selesai merakit pajangan baliho. Dari film laga silat yang tengah merentangkan adegan jurus-jurus tangan kosongnya keudara. Di atas atap gedung bioskop Kamajaya……
***
Banjarmasin, Februari 2017
simak lapak literasi genosida politik 65-66 :
Putusan Akhir Majelis Hakim International People’s Tribunal 65, Rumah Baca (Pustaka) Genosida 65, Kumpulan Tesis dan Disertasi Terkait Genosida 1965; Supersemar, Kudeta Suharto dan Genosida 1965-1966, Kudeta Suharto dan de-Soekarnoisasi : Soekarno telah dibunuh dua kali! , Menggulingkan Soeharto Sekali Lagi : Suara Mereka Yang Kalah, Suara Mereka Yang Menolak Takluk ; Pramoedya Ananta Toer dan Takdir Sejarah Max Lane : Sejarah, 1965 dan Elan Revolusi Indonesia (kompilasi artikel); Hasta Mitra (Tangan Sahabat) : Bertarung Melawan Pembodohan; Buku Kiri, Ultimus dan Bilven Sandalista; “The 1965 Coup in Indonesia: Questions of Representation 50 Years Later” – LITERARY STUDIES CONFERENCE SANATA DHARMA; Lekra, Sastra dan 1965; Putu Oka Sukanta : Menulis Adalah Perjuangan Untuk Hidup, Umi Sardjono, Sulami, Gerwani, Fitnah Lubang Buaya dan Genosida 65, ‘Dance of the Missing Body’ : Mengenali Tubuh Menari dan Sejarah Kekerasan bersama Rachmi Diyah Larasati, Nestapa Eksil 1965, Klayaban di ‘Pengasingan’; Sastra Yang Membela Korban dan Meretas Kabut Sejarah Genosida 1965; Syawal Itu Merah, Cerita-cerita #1965setiaphari; INGAT 65 [Ceritaku ceritamu cerita kita tentang 65], Bioskop Jejak Genosida 65 (bagian 1), Bioskop Jejak Genosida 65 (bagian 2), Bioskop Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (Pramoedya Ananta Toer); Film Sang Penari : Menari Sembari Menumpang Kereta Sejarah… Tsunami Sosial-Politik 1965 Tanpa Menyisakan Luka?, Melawan Tabu dan Kebisuan, Mensubversi Film Propaganda Hitam Pengkhianatan G30S/PKI, Mozaik Jejak Kiri di Indonesia : Kotak Pandora ‘Kejatuhan Suharto’ atawa Habis (di)Gelap(kan) Terbitlah Terang , [arsip] Jejak Kiri Indonesia, Gestok dan Genosida 65 – Cerita Pagi Hasan Kurniawan, [Jasmerah] Sejarah Gerakan Kiri Yang Dihilangkan
Simak juga pameran online genosida politik 65-66 :
PRAKATA LITERASI GENOSIDA 1965-1966, Lorong Genosida (Politisida) 1965-1966, Dadang Christanto, Sanggar Bumi Tarung,Dolorosa Sinaga, Elisabeth Ida Mulyani, Dewi Candraningrum, Yayak Yatmaka, Koes Komo, Nobodycorp. Internationale Unlimited, Komunal Stensil, ,Didot Klasta Harimurti, Made Bayak , Rangga Purbaya, Andreas Iswinarto, TARINGPADI, Obed Bima Wicandra, Mars Nursmono, Gregorius Soeharsojo Goenito, SILENCE & ABSENCE [Adrianus Gumelar Demokrasno – Bunga Siahaan] , Daniel ‘Timbul’ Cahya Krisna, kolaborasi Jagal Bukan Pahlawan!; mozaik rupa : kuburan massal 65-66 bernama ‘indonesia’ ; Awas 30 S Art Project, Daniel Rudi Haryanto, TerrorPaint-Benk Riyadi-Riza-Suhendra-Awank,Rista Dwi I, Koleksi Foto Kamp Konsentrasi Tahanan Politik 65, The Act of Living – Perempuan Penyintas 1965 (feature foto), Okty Budiarti – KAMI BERNYAWA : Butiran Aksara Untuk Tragedi 65, Kharisma Jati (komik), Aji Prasetyo (komik), Arip Hidayat (komik), Evans Poton dkk(komik), Eko S Bimantara (Komik), Museum Bergerak 1965, Museum Rekoleksi Memori, ‘Mwathirika’ and The Victim’s Silent Tale , Kesetiaan, Keteguhan, Kesunyian Hingga Akhir Hayat (Mengenang Basuki Resobowo),
SETJANGKIR KOPI DARI PLAJA hingga NYANYI SUNYI KEMBANG-KEMBANG GENJER [1965 di Panggung Teater], Paduan Suara Dialita : Salam Harapan Padamu Kawan, Spatial History : Pertanyaan Subversi Irwan Ahmett Soal Supersemar (Presentasi Seni) , Prison Song, Musik Tigapagi – Sembojan, Album Lagu Genjer-genjer, Evil Wars In 1965 (Musik Benny Soebardja dkk), The Act of Killing Mixtape (kompilasi musik), Stand Up Comedian Melawan Tabu-Melawan Lupa


